
Alam menjadi kata kunci saat kita membicarakan Kerinci, sebagaimana dikukuhkan dalam konsepsi: Sakti Alam Kerinci. Ini merujuk geografisnya yang dikurung bukit dan gunung. Juga hutan luas, sawah kebun, dan ladang-ladang. Termasuk danau dan sungai-sungainya.
Kesaktiannya terpancar dari kelestarian dan pengelolaan alam. Selain menjadi kawasan terluas Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), bumi Kerinci juga tempat penduduk bertanam berbagai komoditas, di antaranya kopi, teh dan kulit manis.
Kulit manis (casiavera) terbilang paling diandalkan. Tanaman ini menjaga resapan air sebelum ditebang dan digantikan batang yang baru. Kulit manis disebut tanaman tua karena usia panennya menunggu bertahun-tahun. Kadang disebut juga tanaman masa tua sebab jadi andalan tabungan untuk anak kuliah, membangun rumah, menikahkan anak atau naik haji. Sementara pendapatan sehari-hari dari tanaman palawija seperti sayur-mayur, cabe, bawang, singkong, atau pisang yang disebut tanaman muda. Cepat panen, dan sekali sepekan bisa dibawa ke pasar kota atau kampung sekitar, menutupi belanja harian. Itulah sebagian kecil filosofi alam ala peladang Bukit Barisan, khususnya Kerinci.
Bagaimana alam jadi ikon Kerinci dapat pula ditelusuri dari nama-nama yang tergurat di dinding bus malamnya. Pada masa transportasi bus masih jaya (sekarang berganti oto-travel dan kendaraan pribadi) nama-nama bus seperti “Alam Kerinci”, “Anak Gunung” atau “Cahaya Kerinci” lazim dijumpai. Kurun tahun 80-90-an bus-bus tersebut rutin melintas dari Padang melewati jalur Painan-Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan, atau jalur Padang-Muarolabuh, Solok Selatan.
Sekali waktu, pada liburan sekolah, saya menyetop sebuah bus ke Sungaipenuh. Tujuan saya ingin meliput berita di kabupaten tetangga itu. Kebetulan saat itu saya sedang sangat bergairah menjadi koresponden Harian Semangat, Padang.
Di Tapan, kota kecil yang tak kunjung mendapat berkah dari persimpangannya yang potensial itu, jalan bersimpang dua, ke kanan arah Muko-Muko, Bengkulu, dan kiri ke Sungaipenuh, Kerinci. Dulu Kerinci merupakan satu-kesatuan administratif dengan Pesisir Selatan yang disebut Kabupaten Pesisir Selatan-Kerinci (PSK), beribukota Painan, pernah juga di Sungaipenuh dan sebentar di Balaiselasa. Bahkan Gunung Kerinci dulu sebenarnya bernama Gunung Indrapura, dan pernah pula bernama Gunung Kambang.
Tahun 1957 Kerinci dipisahkan dengan Pesisir Selatan, hampir berbarengan dengan Kampar keluar dari Sumbar. Barangkali ini satu upaya politik untuk “menetralisir” peran orang Minang yang dianggap dominan dalam Provinsi Sumatera Tengah. Kerinci kemudian bergabung dengan Jambi, sama dengan Kampar yang masuk Propinsi Riau. Nama gunung tertinggi di Sumatera itu pun berubah jadi Gunung Kerinci.

Secara administratif Kerinci dan Sungaipenuh kini sudah dipisahkan. Sungaipenuh yang semula merupakan ibukota Kabupaten Kerinci, sejak tahun 2008 berstatus sebagai kota otonom, dan ibukota Kabupaten Kerinci pindah ke Siulak.
Tapi hubungan suatu daerah tak bisa hanya dilihat secara administratif. Hubungan historis-kultural jauh lebih signifikan. Maka menyebut “alam” di Sungaipenuh atau Kerinci, hakikatnya merujuk kedua wilayah kultural ini.

Perjalanan ke Kerinci
Tiap kali pulang kampung, saya selalu merasa dihimbau untuk datang ke Kerinci. Mungkin karena pengalaman saya berkunjung dulu begitu membekas. Saya sudah berjanji kepada keluarga yang saya ajak jauh-jauh dari Yogya untuk ke sana, tapi ternyata selalu luput. Baru pada pulang terakhir, penghujung 2019 lalu, atau tiga bulan sebelum pandemi covid 19, saya berkesempatan pergi bersama keluarga.
Kami berangkat agak siang sebab pagi hari saya mengisi acara di Pondok Pesantren Darul Ulum, Lunang. Gerimis membuat saya hampir menunda keberangkatan. Pikir saya, menginap dulu di Tapan, besok baru “naik” ke Bukit Barisan. Tapi Mas Suyatmin Widodo, pengasuh PP Darul Ulum meyakinkan saya bahwa jalan Tapan-Sungaipenuh sekarang sudah bagus. Aspalnya mulus dan kendaraan juga ramai. Saya senang mendengarnya, sebab itu yang saya harapkan dari kedua wilayah “serumpun” ini.

Untuk menjangkau Kerinci ada tiga jalur utama. Selain dari Pesisir Selatan, bisa lewat Solok Selatan dan Merangin atau Bangko. Alternatif lain, via Bandara Depati Purbo rute Jambi, Padang, Pekanbaru, Palembang, Batam, Jakarta dan Kualalumpur.
Perbatasan Kerinci-Pessel atau Sumbar-Jambi terletak di Desa Sako, Kecamatan Ranah Ampek Hulu. Sungai Sako mengalir jernih di sisi jalan, membelah perbukitan. Sako dikenal sebagai area rumah makan di mana bus-bus atau kendaraan berhenti mengaso sebelum memasuki hutan. Di daerah sumber air ini sekarang banyak didirikan tempat rekreasi berupa kolam renang. Ini kreatifitas ekonomi warga yang perlu didukung.
Kami berhenti sejenak di gerbang perbatasan. Minum kopi di sebuah warung terpal sembari mengecek apakah BBM mobil aman. Tukang warung menyarankan untuk mengisi bensin sebab pesawangan (tempat sepi) akan panjang. Ia menunjuk sebuah rumah yang menjual bensin eceran. Kami putuskan mengisi bahan bakar di tempat dimaksud.

Jalan memang sudah mulus. Even Tour de Singkarak 2019 yang untuk kali pertama memasukkan Propinsi Jambi (khusus Kerinci) sebagai jalur lintasan, berkah bagi jalur ini. Tapi jalan tetap sempit. Pelebaran terkendala tebing, meski bukan tak mungkin. Pelebaran bertahap bisa dilakukan. Sementara menunggu pelebaran jalan, perlu dipikirkan pagar beton supaya jurang tidak rawan.

Meski berapa kali lewat jalur ini, baru saat itulah saya bergidik melihat jurangnya. Padahal dulu jalan lebih mirip kubangan badak. Bus meraung dan berkali-kali kernet turun mengganjal ban. Mungkin pengaruh waktu saat melewatinya. Dulu, saya melewatinya di atas bus malam saat penumpang tertidur dan jurang gelap tak tertangkap mata telanjang.
Setelah pendakian terlewati, sampailah kami di Bukit Impian dari mana kota Sungaipenuh dan sebagian alam Kerinci mulai terlihat. Tapi kabut yang mulai turun bersama rintik hujan mempercepat kelam, menghablur pandangan.
Menjelang magrib, kami masuki gerbang kota Sungaipenuh. Ini bertolak belakang dengan jadwal kedatangan saya dulu jika naik bus malam, biasanya bus masuk kota sesaat sesudah azan subuh. Kami berhenti sejenak di Lapangan Merdeka dengan monumen Monas mininya. Lapangan itu ramai sebab sedang ada pasar malam.

Tak jauh dari Lapangan Merdeka, kami masuki sebuah rumah makan Padang. Dendeng batokok menjadi menu saya untuk bernostalgia. Malamnya kami menginap di Hotel Citra Alam di sekitaran Bukit Sentiong. Hotel di Sungaipenuh relatif banyak dan gampang dicari, harga bervariasi antara 250.000-500.000 permalam.
Hotel Citra Alam berada di ketinggian sehingga kota Sungaipenuh terlihat hampir keseluruhan. Di bagian lain, jalan menuju Tapan tampak mengular dalam kabut, nun di ketinggian pegunungan. Pihak hotel juga menyediakan semacam menara pandang di lantai paling atas, dan dari sana ketika sinar matahari menyemburat bersama embun, kabut yang berpulun terangkat pergi, dan terlihatlah kemilau indah tanah Kerinci.
Perkembangan Sungaipenuh
Setelah sarapan dan mandi air hangat di hotel (mandi air dingin membuat saya menyerah!), kami datang ke Masjid Agung Kerinci di Pondok Tinggi. Ini sebuah masjid tua berbahan dasar kayu hutan. Di sekitar masjid masih terdapat sejumlah rumah panggung, rumah asli orang Kerinci. Tentang masjid ini pernah saya tulis di www.tarbiyahislamiyah.id (Mei 2020).

Dari masjid tua itu kami raun-raun sejenak dalam kota. Melewati pasar raya dengan suasana yang hidup dan sayuran hijau yang terasa ikut menghijaukan mata. Kerinci memasok sayur-mayur untuk daerah pesisir. Di pasar kampung saya, terkenal lado (cabe) Kerinci dan kopi Nur. Tahun 70-80-an, orang kampung saya juga banyak berladang di Kerinci. Nenek saya berladang di Jujun, arah Danau Kerinci atau ke kaki Gunung Raya dan Makurai. Pada masa Kesultanan Indrapura, Kerinci merupakan hinterland pemasok hasil bumi. Teh Kerinci di Kayu Aro pernah diusulkan untuk diekspor melalui pelabuhan laut Muarosakai di Indrapura. Kala itu jalan darat ke Teluk Bayur Padang hancur-lebur, sedang jarak ke Jambi dua kali lipat dibanding ke Padang. Tapi tak digubris pihak terkait.
Sungaipenuh tampak kian padat. Hotel, perkantoran, pertokoan dan perumahan berderet rapat. Semoga saja izin dan pembangunannya betul-betul memperhatikan jalur gempa dan patahan. Pada 7 Oktober 1995 Kerinci pernah dihoyak gempa besar. Itu bisa jadi momentum untuk memperhatikan teknik bangunan.
Sebagaimana kota di daerah pegunungan, jalan-jalannya relatif sempit sebab kontur tanah dan pola lahan. Sungaipenuh juga seperti itu. Jalannya sempit dan pendek, sementara jumlah kendaraan makin banyak, sehingga kepadatan jalan raya tak terhindarkan. Kalau sudah begitu, cuaca dan alam yang sejuk terasa panas. Ke depan, sebagai kota yang sedang berkembang, Sungaipenuh mesti memperluas wilayahnya sesuai dengan perencanaan tata ruang, tentu tidak mengorbankan lahan produktif.
Tak Ada Lagi Enceng Gondok
Puas berkeliling kota, kami bergerak menuju Danau Kerinci. Kami mampir kembali di warung Padang tadi malam, memesan nasi bungkus yang hendak kami santap di tepi danau. Ada dua jalur utama yang bisa ditempuh. Jalur ke Sanggaran Agung atau ke Lolo, nanti bisa bertemu kalau keliling danau. Kami pilih jalur Lolo.
Meski tak terlalu kentara, jalan dari kota arah ke danau sebenarnya menurun. Pemandangan alamnya indah dan suasana sekitar menyenangkan. Kampung dengan rumah-rumah kayu bertiang tinggi, tampak kokoh dan mencuat di antara rumah beton masa kini yang dicat warna-warni. Di kampung lain yang cukup padat, kendaraan merayap pelan. Ternyata sedang ada pesta perkawinan dan tenda didirikan di sebagian badan jalan. Pengantin diiringi pesumandan, tak jauh beda dengan acara pernikahan di Pesisir Selatan.

Selepas simpang jalan ke Bandara Depati Purbo, pemandangan berganti hamparan sawah hingga ke tepi danau. Kondisi jalan mulus dilapisi beton. Saya teringat puluhan tahun lalu, jalan ke Danau Kerinci dipenuhi danau-danau kecil.
Jarak sekitar 15 km itu segera menghantar kami ke tepi danau. Kami bentang tikar di bawah sebatang pohon rindang dan membuka bungkusan nasi Padang. Angin danau berhembus lembut. Meriakkan air danau. Ombak-ombak kecil muncul di tepi ketika satu-dua perahu lewat. Beberapa orang pemancing duduk menunggu jorannya ditarik ikan. Tak jauh dari kami ada sebuah restoran terapung. Lumayan ramai. Dalam hati saya merasa senang bahwa fasilitas seperti restoran ada di sini, sebab dulu hanya ada warung-warung ala kadarnya.
Satu hal lagi yang saya syukuri adalah permukaan danau relatif bersih dari eceng gondok. Padahal dulu eceng gondok hampir menutupi permukaan danau. Bagaimana membersihkannya, saya belum punya informasi. Apakah eceng gondoknya musnah sendiri atau dibersihkan oleh pihak terkait dengan suatu cara? Entah. Barangkali pihak berwenang yang menangani danau di Indonesia bisa belajar ke Danau Kerinci.
Salah satu danau yang parah terkena serangan eceng gondok yang pernah saya lihat adalah Danau Limboto di Gorontalo. Sudah seperti tanah rawa. Secara ekologis, danau memang kawasan paling parah kerusakannya di Indonesia, namun kurang terekspos. Menurut suatu data, lebih 70% danau di Indonesia dalam kondisi kritis!
Air Hangat Semurup dan Kayu Aro yang Dingin
Perjalanan kami lanjut ke kebun teh Kayu Aro. Tapi kami singgah dulu di air panas Semurup. Ini merupakan sumber air panas vulkanik yang menggelegak terus-menerus. Para pengunjung memanfaatkannya untuk merebus telur, jagung, kacang atau pisang. Bahan-bahan itu disediakan pedagang lengkap dengan tali atau jaring kecil sehingga bisa langsung dicelupkan ke air yang mendidih.
Air hangat Semurup ini boleh dibilang destinasi klasik. Jauh semasa saya kanak, namanya sudah sering saya dengar. Ada juga cerita horor yang sering mengiringi. Konon, sudah beberapa kali terjadi orang terjun ke dalamnya, bunuh diri. Saya tak tahu kebenarannya. Tapi saat saya mengunjunginya dulu, sumber air panas memang dibiarkan terbuka begitu saja. Tak ada pagar dan penjagaan. Sekarang sumber air panas sudah dipagar tinggi. Kita hanya bisa melihatnya dari luar dan menikmati aliran airnya melalui jalur-jalur yang dibuat khusus. Area dilengkapi kamar mandi dengan pancuran air panas. Ada juga gazebo untuk istirahat, mushala dan fasilitas lain.

Air belerang panas ampuh mengobati penyakit kulit, rematik atau cocok dinikmati sebagai kehangatan alami. Saya dan anak-anak membeli telur puyuh, kacang dan pisang, lalu dicelupkan ke air yang mendidih. Asapnya mengepul ke udara. Sambil menunggu makanan masak, saya merendam kaki di aliran air yang dibuat berkelok-kelok sehingga air yang panas berubah jadi hangat atau suam-suam kuku. Lumayan menghilangkan penat. Lebih dari itu, air hangat Semurup mengingatkan saya pada alam Kerinci yang lain: daerah vulkanik dan patahan.

Menjelang sore kami sampai di kebun teh Kayu Aro, perkebunan teh tertua dan terluas di Sumatera. Dirintis pembukaannya oleh Namlodse Venotchaaf Handle Veriniging Amsterdam (NV HVA) sepanjang tahun 1925-1928. Tenaga kerjanya didatangkan dari Jawa sehingga sampai sekarang banyak warga keturunan Jawa yang menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari dan mempertahankan budayanya.
Saya teringat kunjungan saya dulu di Kayu Aro. Saat itu saya datang saat lebaran ke Aroma Pico, sebuah tempat wisata di tengah perkebunan. Warga merayakan libur Lebaran dengan bersampan di telaga, naik komidi putar dan menonton seni pertunjukan. Di situlah saya menonton kuda lumping/kuda kepang pertama kali. Malamnya saya meronta-ronta kerasukan sambil menirukan pemain kuda kepang makan beling. Saya baru mengetahuinya setelah diceritakan tuan rumah tempat saya menginap.
Luas perkebunan teh Kayu Aro mencapai 2.590 hektar. Teh olahan pabrik Kayu Aro diekspor ke Eropa dan konon menjadi kesukaan Ratu Elizabeth dan Ratu Welhilmena. Selain pabrik yang terus beroperasi, di Kayu Aro terdapat banyak rumah bergaya indisch tempat tinggal karyawan dan para mandor. Rumah-rumah peninggalan kolonial itu masih terjaga dengan bunga-bunga yang segar di tiap halamannya.

Pemandangan utama di Kayu Aro selain hamparan hijau kebun teh tentu saja keperkasaan Gunung Kerinci. Cukup mencari tempat aman di tepi jalan, atau nongkrong di sebuah warung, maka pemandangan luar biasa akan kita dapatkan.
Malam itu kami menginap di sebuah homestay sederhana di Kersik Tuo, B. Darmin, yang pintu dan jendela-jendelanya menghadap lurus ke puncak Gunung Kerinci. Kersik Tuo merupakan pintu masuk untuk pendakian. Bagian bawah homestay ditempati keluarga tuan rumah dan kami di lantai atas. Kamarnya luas dengan kursi-kursi tertata seperti rumah kuno. Di bawahnya menghampar kebun teh laksana karpet hijau yang mengombak ditiup angin gunung. Pagi hari juga terlihat kesibukan di sekitar Tugu Macan di mana petani dan pengumpul sayur menurunkan dan memuat kol, sawi, tomat dan sebagainya ke atas pick-up.
Berada di tengah kebun teh Kayu Aro waktu seolah berhenti. Pikiran menjelajah dan menyentuh langsung apa yang disuguhkan alam raya. Saya tak akan membahas tentang sejarah dan destinasi teh Kayu Aro lebih lanjut, dan tidak pula akan mengabsen semua destinasi Kerinci. Saya hanya ingin menyatakan bahwa mengingat Kerinci, sama dengan mengingat panggilan alam. Datang memenuhi panggilan itu, membuat kita berjumpa dengan kemurnian alam di satu sisi dan budi daya yang lestari di sisi lain.
Ke mana pun Anda melangkah dan destinasi apa pun yang dipilih, apakah Danau Kerinci, Puncak Kayangan, air panas Semurup, kebun teh Kayu Aro, Air terjun Tujuh Tingkat, Danau Tujuh Warna, sebuah perkampungan atau mendaki ke puncak Gunung Kerinci, alam akan selalu menyapa. Gunung, bukit, hutan, sungai, dan segala yang hijau dan biru menyatu, memanggil-manggilmu dari tiap penjuru.
Raudal Tanjung Banua (lahir di Taratak, Pesisir Selatan, Sumatra Barat, 19 Januari 1975) adalah sastrawan Indonesia yang banyak menulis puisi dan cerita pendek. Raudal pernah menjadi koresponden Harian Semangat dan Haluan, Padang. Raudal menyelesaikan studinya di Jurusan Teater Yogyakarta. Karyanya yang berupa puisi, cerpen dan esei dipublikasikan di pelbagai media massa dan antologi.



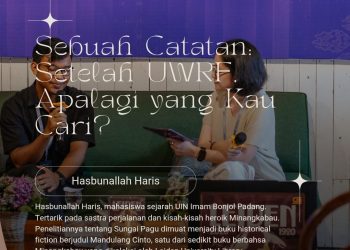

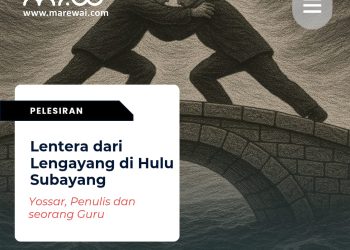
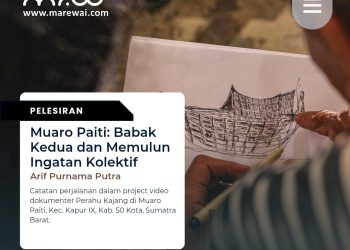


Discussion about this post