
Sepatu kanan Marisa sudah jatuh. Selangkah lagi dia maju, maka tamatlah kehidupannya. Matanya terpejam kuat-kuat. Mulutnya memaki manusia-manusia yang telah meruntuhkan kebahagiaannya. Sore ini, gedung berlantai puluhan yang terkenal menjadi tempat bunuh diri adalah pilihannya untuk meregang nyawa. Tetapi suara decak seseorang terdengar dari arah belakang. Mengganggu niatnya yang tinggal sejengkal lagi lenyap. Kepalanya sedikit menoleh; mengintip dari ekor mata, melihat kehadiran manusia penceramah. Bukankah ini seperti di kejadian film-film? Seorang penyelamat datang untuk menggagalkan aksi bunuh diri si tokoh utama lalu mereka hidup bahagia. Tapi tidak kali ini, karena yang hadir adalah seorang perempuan.
“Pergilah sebelum kamu menjadi saksi atas bunuh diriku!”
Marisa sebenarnya mulai takut dengan ketinggian gedung. Kepalanya berkunang-kunang. Pelipisnya pusing dan hidungnya sedikit tersumbat karena angin menyerbu wajahnya. Otaknya banyak berasumsi; apakah dia akan langsung mati, atau Tuhan masih menyelamatkan nyawanya dan ia hidup lebih menderita dengan tubuh yang hancur?
“Sudah sering, jadi nggak kaget lagi kalau jadi saksi atas tiap-tiap manusia bodoh yang bunuh diri di gedung ini.”
Manusia bodoh? Marisa tertawa getir, masih memunggungi orang asing itu. Bukankah semua manusia di muka bumi ini bodoh? Sering melakukan kesalahan hingga manusia lain mengikutinya. Menjadi rangkaian alur kehidupan yang begitu kejam dan memuakkan. Jadi, untuk apa ia melanjutkan hidup bersama manusia-manusia itu di dunia ini? Pikiran Marisa semakin liar dan tak henti mengembangkan asumsi-asumsi buruk lainnya.
Suara langkah dari arah belakang terdengar. Marisa memperingatkan, “Jangan mendekat atau aku terjun sekarang juga!”
“Silakan! Tapi mungkin kamu nggak akan langsung mati. Mungkin saja bisa patah kaki sebelah, atau wajahmu hancur tak karuan, atau … yang paling parah–”
“Berisik!”
Kemarahan Marisa mencuat, tercampur kebencian mendalam pada manusia-manusia yang sebelumnya ia temui. Dia kesal dengan berbagai asumsi yang sedari tadi berkembang di otaknya disebutkan oleh orang di belakangnya secara terang-terangan. Pandangannya kembali jatuh dan itu masih mengerikan baginya. Tenggorokannya kering, susah menelan saliva yang terasa mengeras. Tuhan benar-benar menyiksanya di dunia ini.
“Sudah pernah pergi ke Mars belum?” Pertanyaan aneh keluar tiba-tiba dari orang asing itu, “kalau belum, coba daftar jadi kelinci percobaan NASA.”
Marisa memberanikan diri memutar tubuhnya; menghadap wajah perempuan yang sedari tadi mengoceh. Rasanya ingin sekali menyumpal mulut perempuan itu dengan kaus kakinya. Agar tak banyak bicara dan pergi meninggalkannya dengan kebingungan –apakah dia jadi bunuh diri atau tidak.
Setelah melihat tampilan perempuang itu, Marisa tertawa remeh, “Ternyata masih anak sekolahan.” Dia menyilangkan kedua tangannya, “lebih baik belajar yang rajin, nggak perlu peduli sama urusan orang lain!”
Mendengar ejekan dari Marisa, perempuan berseragam sekolahan itu berkata, “Sempit sekali pikiranmu. Lihatlah inti bukunya, bukan kovernya. Ini bukan tentang siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan.”
Marisa tidak peduli dan kembali memutar tubuhnya, siap melompat. Sejenak, dia menatap tanah basah bekas hujan semalaman. Tubuhnya pasti tidak akan hancur dengan mudah, tetapi nyawanya akan cepat hilang karena ketinggian gedung. Rambut hitam panjang Marisa berterbangan. Wajahnya tersapu dinginnya udara sore. Tidak ada yang bicara lagi. Marisa mendapatkan ketenangan yang begitu mendalam.
Sepuluh detik… dua puluh detik… tiga puluh detik….
“Kok, belum lompat juga?” Suara menyebalkan itu terdengar lagi. Mengacaukan konsentrasinya dalam eksekusi pengakhiran hidupnya. “Kenapa? Berubah pikiran ya, untuk daftar jadi kelinci percobaan NASA ke Mars?”
Marisa kembali melihat tampilan perempuan berseragam putih abu-abu dengan geram. Raut wajahnya tampak siap menerkam si perempuan remaja. Tapi emosinya berhasil dikendalikan, karena dia harus mengakhiri hidupnya agar semua permasalahannya juga berakhir.
“Atau begini, aku punya informasi tentang pendaftarannya,” ucapnya mengeluarkan ponsel dari tas, “sebentar, yah!”
“Diam!” bentak Marisa. “Gue mau bunuh diri!” katanya meyakinkan perempuan itu dan juga dirinya.
“Oh, yaudah, aku tungguin sambil duduk, biar aku langsung telepon polisi kalau ada kejadian bodoh lagi di TKP yang sama.”
Marisa benar-benar melihat remaja itu duduk di lantai bersemen. Sekarang keraguan mulai merayap saat tubuhnya kembali siap terjun. Bagaimana jika benar dia tidak langsung mati ketika jatuh?
“Duh, udah lebih dari satu menit nggak lompat juga. Bisa cepetan nggak? Orang rumah pasti nungguin aku.”
Berbagai permasalahannya memudar seketika, tergantikan rasa kesal pada remaja itu. Marisa turun dari balkon dan menghadapnya secara perlahan. “Memang sudah berapa banyak yang bundir di sini?” Tiba-tiba ia penasaran soal itu.
Perempuan remaja itu bangkit dan mengangkat bahunya tak yakin, “Sekitar belasan atau mungkin sudah dua puluh.”
“Langsung mati?”
“Enggak. Ada yang patah tulang punggung, kulih wajahnya robek, sebelah kakinya patah, kadang tangan juga. Hm, tapi ada sih yang langsung mati.”
“Bagaimana caranya?”
“Ya dia lompat sambil tusuk pisau ke perutnya.”
Wajah Marisa bergidik ngeri. Pisau? Dia bahkan memiliki phobia tersendiri dengan benda tajam itu. Terakhir kali dia mengalami perampokan tas dan ditodong pisau, dia memilih untuk merelakan tas mahalnya bersama dengan segala isinya. Pandangan Marisa jatuh menatap lantai bersemen. Mengingat bagaimana berbagai permasalahan mulai menyerang hidupnya secara berurutan. Mulai dari keluarga yang pecah belah tak mengunjunginya lagi. Sampai hubungan percintaan yang berakhir kekecewaan dengan tanggungan di dalam perutnya.
Melihat keheningan yang tercipta dari Marisa, perempuan remaja berkata, “Aku tidak perlu tahu semua permasalahanmu. Jujur, aku bosan dengar cerita kalian semua, rata-rata alasannya tidak lain dari percintaan, keluarga, pekerjaan, atau teman.” Dia berjalan maju dua langkah.
Marisa yang merasa didekati mengangkat sebelah tangannya. “Jangan mendekat, aku masih punya niat bunuh diri!”
“Kamu pernah naik pesawat?”
“Pernah.”
“Saat kamu berada di atas pesawat, tentunya kamu melihat manusia dan segala isinya yang di bawah tampak kecil, bukan?” Marisa mengangguk.
“Pernah berpikir bahwa sebenarnya masalah kita juga ikut mengecil di bawah sana?” Marisa menggeleng tidak yakin.
“Cobalah pikirkan! Selain masalahmu akan tampak kecil dibanding urusan lainnya yang lebih penting, masalahmu juga akan lenyap dimakan waktu. Kamu boleh percaya atau tidak soal itu.”
Memikirkan apa yang baru saja didengar, Marisa memejamkan matanya. Mengingat berbagai ketidakadilan yang diterima selama hidup. “Kamu tidak tahu seberapa berat permasalahanku.”
“Aku sudah bilang, aku tidak perlu tahu semua permasalahanmu. Aku hanya mencoba untuk membuka pikiranmu.”
“Kamu pikir kamu berhasil? Sudah berapa orang yang kamu gagalkan untuk bundir?”
“Aku tidak ingat.”
“Cih! Kamu masih anak sekolah, masalahmu tidak seberatku. Asal kuberitahu ya, kamu akan merasakan pahitnya hidup ketika mencapai di usiaku sekarang ini.”
Tanggapan si remaja sungguh tak diharapkan Marisa. Tersenyum menjengkelkan sambil menggelengkan kepala. “Kamu tidak paham juga ternyata. Aku tidak membahas masalahnya, tapi aku ingin membetulkan otakmu yang bengkok.”
Otaknya bengkok katanya? Dia tidak terima. Wajah yang sebelumnya tampak menyedihkan berubah menjadi monster.
“Jangan marah, aku tidak berniat mencemoohmu. Manusia yang hendak bundir memang terkadang otaknya bengkok. Jadi, aku perlu meluruskannya,” katanya meyakinkan Marisa. “Kamu pernah dengar cerita manusia-manusia yang sudah mati di kuburannya meminta sesuatu?”
Sekarang apa lagi? Pikir Marisa.
“Ah, ternyata kamu tidak tahu. Tenang, bukan hanya kamu yang tidak tahu, tapi orang-orang yang hendak bundir juga tidak tahu,” ucapnya tersenyum dan menggelengkan kepala, “biar kuberitahu ya, manusia-manusia yang sudah hidup di alam kuburnya selalu meminta pada Tuhan untuk dibangkitkan kembali di dunia.”
“Benarkah? Untuk apa? Memangnya bisa begitu?” Marisa melebarkan sorot matanya, tidak percaya.
Remaja itu mengangguk, “Yah, mereka ingin dikembalikan ke dunia agar bisa berbuat banyak kebaikan pada orang lain.”
“Aku tidak percaya. Tuhan pasti tidak akan mengabulkan permintaannya, karena manusia itu pasti akan bertindak bodoh lagi di dunia.”
“Sepertimu?”
Marisa terdiam dan tubuhnya terbujur kaku mendengar pertanyaan menikam. Dia bahkan tidak berani beradu pandang pada remaja itu. Sekarang dia paham. Bukan hanya manusia-manusia menyebalkan dan menghancurkan dirinya yang bodoh, tapi juga dirinya.
“Sekarang kamu sudah mengerti. Baiklah, jadi sekarang apa rencanamu? Melupakan semua masalah dan melanjutkan hidup menjadi orang yang lebih baik?”
Perlahan Marisa mengangkat wajahnya dan tersenyum getir. Air matanya kembali menetes, tetapi dengan makna berbeda. Tubuhnya kembali menaiki balkon, yang membuat remaja itu kebingungan.
“Aku akan pergi ke Mars,” jawab Marisa sambil menjatuhkan diri dan menghilang dari pandangan remaja yang terkejut.
BIODATA PENULIS
Putri Oktaviani lahir di Tangerang Tahun 2000. Alumnus Akuntansi, Perguruan Tinggi Swasta. Senang menulis novel dan cerpen. Karya tulisnya terpercik di media online dan platform digital seperti; Magrib Id, Takanta, Marewai, Literasi Kalbar, Cerpen Sastra, Novel Life, dan Fizzo. Cerpennya berjudul Setelah Ledakan Juara 1 Lomba Cerpen Loka Media. Penyuka coklat keju dan sambal goreng kentang. Penikmat podcast horor. Bisa disapa via IG @putri.oktavn


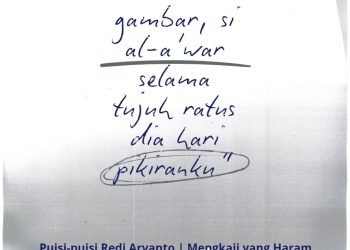




Discussion about this post