Kami saling pandang, masih menduga-duga alasan di balik keputusannya. Ini sungguh mengagetkan, seorang guru mengaji tiba-tiba memutuskan pindah menetap ke kampung yang dihuni para bajingan.
“Alasannya apa?” Mang Somse menguatkan pertanyaanku.
Ahmad Kosim menarik nafas yang berat sebelum bersuara lagi, “dua minggu lalu istriku mati terlindas truk saat aku ngumandangkan adzan di mesjid Babakan. Aku pikir Tuhan sedang ngantuk atau sedang ketinggalan catatannya saat kejadian itu. Tapi aku tak sepenuhnya yakin Tuhan sedang khilaf mengambil nyawa istriku saat aku menyembahnya. Aku akhirnya berpikir Tuhan menyia-nyiakan pengabdianku,”
Ia menarik nafas lagi setelah bercerita dengan kalimat panjang. Nampak wajahnya tertekan.
“Sejak kejadian itu, aku pikir Tuhan lebih setuju kalau aku pamit dari kampung Babakan, meninggalkan masjid, meninggalkan anak-anak ngajiku, meninggalkan semua ibadahku,” suara Ahmad Kosim terdengar serak. Ia seperti sedang menemukan tempat menghempaskan keluhan atas kekecewaannya pada takdir Tuhan.
Aku merasa tertohok mendengar penuturan ahmad Kosim. Bagaimana bisa seorang laki-laki yang selama ini mengabdi begitu dalam kepada Tuhannya, tiba-tiba mengubah rencana hidup hanya karena kehilangan satu nyawa?
Lelaki berkopiah itu masih berdiri mematung di hadapan kami. Kupandangi detail wajahnya sekedar melunaskan rasa penasaranku untuk sebuah kata bernama “iman”. Kucari-cari di sorot mata dan garis wajahnya, sekiranya ada kata itu yang bisa meyakinkan aku kalau selama ini dia tak serius mengabdi kepada Tuhannya. Kalau dia serius menjadi pengabdi Tuhannya, kupikir tidak akan mudah ingin meninggalkan rumah Tuhan yang telah sekian waktu diramaikannya. Sayangnya aku tidak menemukan bayang kata “iman” itu di wajahnya. Ah, betapa sok tahunya aku tentang “iman”.
“Boleh, toh?” terdengar kalimatnya pendek bertanya.
Kulirik lelaki lain yang ada di dalam kedai Mang Somse, Aku memberi kode dengan mengangguk kepada mereka. Maksudku agar kedatangan Ahmad Kosim diterima saja. Hitung-hitung menambah jumlah lelaki yang bisa diajak main kartu.
Mang Somse dan lelaki lainnya sepertinya cepat mengerti dengan kode yang kuberikan. Mereka turut mengangguk tanda setuju.
“Oke, Mas kami bolehkan pindah sini,” Mang Somse mewakili kami semua, menyanggupi permintaan Ahmad Kosim. Keputusan Mang Somse disambut dengan senyum nyengir oleh lelaki tersebut.
Tak banyak lagi yang ingin kami tanyakan atau interogasi dari Ahmad Kosim. setelah dia bercerita penyebab keinginannya pindah ke kampung Perobek. Kami terima lelaki bermata sedikit sipit itu dengan senang hati. Kami panggil dia bang Upret karena sejarah masa lalunya adalah seorang ustad dari kampung Babakan yang terkenal alim penghuninya. Alasan kami menerima kepindahan lelaki itu bukan karena kenaifannya mengubah jalan hidup menjadi membelakangi Tuhan adalah gambaran yang sama dengan kehidupan kami yang bajingan-bajingan. Penerimaan itu semata-mata karena rasa senasib yang mendadak menjalari batin–bagaimana rasa senasib itu datang, itu bukan pertanyaan cerdas. Kami penghuni kampung Perobek adalah para bajingan yang sudah merasa mampus mimpi bahagianya jauh sebelum bang Upret datang, tetapi kami masih memiliki kepedulian dengan sesama.
**
Setelah menetap di kampung Perobek, bang Upret sungguh mengubah semua rupa penampilannya. Ia tidak lagi memakai kopiah. Janggutnya ia tebas habis. Celananya berganti dengan jeans robek. Gamis putih berganti dengan kaos lengan pendek seperti kebanyakan dipakai laki-laki kampung Perobek. Peristiwa kematian istrinya yang tragis telah memutar haluannya sangat tragis. Kini Ahmad Kosim adaah bang Upret yang seharai-hari mencari makan dari pekerjaan tukang parkir di pasar Senen. Ia telah meleburkan hidupnya ke dalam dunia yang meniadakan ibadah apa pun. Dunia dari sekian belas rumah bedeng yang dihuni orang-orang tak tercatat di jalan lurus kampung Petobek. Dunia orang-orang yang menaruhkan otot dan kekerasan di statsiun Senen agar bisa bertahan hidup. Ada Mang Somse, pencopet yang nyambi buka kedai kopi pada malam hari. Juga ada bang Jono, pengemis yang setiap hari mangkal di depan pasar Senen dengan lagak pura-pura cacat kaki kiri. Lalu aku, Samson, pemulung berkaki pincang. Selain aku, ada bang Udel, dan belasan aki-aki peot di komplek yang cari hidup sebagai jambret, pemulung, pengedar, tukang jagal, dan segala macam pekerjaan busuk lainnnya. Kamilah yang menamai kampung Perobek; singkatan dari Perkumpulan Orang-orang Brengsek.


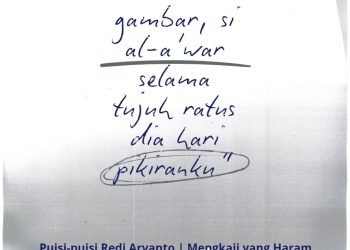




Discussion about this post