
“Manusia itu tempatnya lupa,” demikian Tipang mengawali perbincangan di hadapan kawannya, Siwat.
Siang itu, Tipang dan Siwat tengah terduduk lesu di bawah pohon ara yang rimbun. Ranting-rantingnya bertiup ke selatan, searah dengan angin yang berembus halus, menyebabkan beberapa daun rontok. Tipang, lelaki berbadan agak tambun itu memang gemar menelurkan berbagai pernyataan bijak. Sementara Siwat, seorang pemuda yang baru saja lulus dari perguruan tinggi, yang sedari tadi hanya termangu, sudah beberapa pekan ke belakang menjadi pendengar setianya.
“Ya,” balas Siwat, “aku sudah tahu perkara itu jauh sebelum kamu mengucapkannya.”
“Tidak, Wat. Kamu sama sekali tidak mengerti apa yang kumaksud.”
“Jadi?”
“Percaya atau tidak, kamu sebetulnya adalah pengusaha tambang dan aku adalah seorang pemimpin partai.”
Air muka Siwat seketika masam. Keningnya berkerut bagaikan pematang sawah. Beriringan dengan itu, mulut Siwat terus-menerus mengepulkan asap dari sebatang keretek yang ia bakar sepuluh menit sebelumnya. Ia mencari-cari balasan untuk menimpali perkataan Tipang tersebut, namun hanya berujung suara dahan jatuh. Suasana masih lengang seperti sediakala. Di tengah keheningan itu, Tipang mencomot gelas berisi es jeruk perasan miliknya.
“Lihat, kan?” sambung Tipang dengan senyum yang mulai tersimpul, “tampak sekali di wajahmu bahwa kamu kebingungan.”
Siwat tak dapat mengelak dari penafsiran spontan Tipang, yang tersohor di kampungnya lantaran sering menerawang jauh ke masa depan meski kakinya tak pernah menapak ke luar pulau dan sehari-hari hanya mengumpulkan kelobot jagung untuk dijual ke perangkat desa. Bibir tipis Siwat, yang kini sudah mulai menghitam akibat tumpukan nikotin, sudah tak tahan untuk komat-kamit.
“Aku? Seorang pengusaha tambang?” tukas Siwat.
“Tepat sekali! Bahkan, pengusaha tambang yang sangat sukses.”
“Entah apa yang sedang merasuki kepalamu itu, Bang. Tapi, aku bukanlah pengusaha tambang dan kamu tidak sedikit pun mencerminkan seorang pemimpin partai.”
“Jangan salah, Wat, aku ini sesungguhnya adalah orang yang mengepalai ribuan kader partai pemenang pemilu.”
Siwat tersedak oleh tembakaunya. Wajahnya sontak memerah. Baru kali ini ia tertawa terbahak-bahak lebih dari sepuluh puluh detik. Setelah merasa puas, dua jemarinya menyentil puntung rokok hingga masuk ke tong sampah bundar yang tergeletak tak jauh dari sisinya. Siwat lalu melirik Tipang yang masih terdiam menikmati awan gemawan di angkasa, seolah-olah tak mengacuhkan ejekannya itu.
“Maaf, Bang,” kata Siwat, “tapi mana ada pengusaha tambang yang mengaso di bawah pohon ara bersama seorang pemimpin partai pemenang pemilu?”
Tipang menoleh sebentar, sebelum matanya menjurus ke batang ara yang besar dan berdaging, lalu mencolek pinggang Siwat.
“Manusia itu tempatnya lupa,” ulang Tipang lagi, “masa, kamu sudah lupa dengan ucapanku barusan?”
“Yayaya, lantas?”
“Saat masih berada di dalam kandungan, masing-masing dari kita ditanya oleh malaikat sebanyak tujuh puluh tujuh kali, dan sebanyak itu pulalah kita menjawab ‘iya’—dalam bahasa apa pun itu—sambil mengangguk,” ungkap Tipang dengan yakin.
Tipang, yang kini sadar dirinya telah memegang kendali atas forum tersebut, sesekali meregangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan lalu kembali menenggak es jeruk perasan yang masih tersisa separuh. Sementara di sampingnya, Siwat kembali menyalakan kereteknya yang kedua seraya mengusap-usap dagunya yang setengah botak. Tipang mengatakan bahwa tiap manusia sudah terlebih dulu ditunjukkan jalan hidupnya, dari lahir sampai wafat, ketika masih empat bulan dalam kandungan secara terperinci tanpa ada satu pun bagian yang terlewatkan, bahkan jika fragmen itu lebih kecil dari biji atom.
“Cukup adil dan demokratis, bukan? Kita saja yang lupa.”
“Oh….,” kepala Siwat berdenging, mencoba memindai makna di balik kalimat temannya itu.
“Konkretnya,” jelas Tipang perlahan-lahan, “kamu dan aku sudah sama-sama ditanya oleh malaikat sebanyak tujuh puluh tujuh kali dan menyatakan sepakat sebanyak tujuh puluh tujuh kali bahwa kita akan bertemu di sini, di bawah pohon ara ini, jauh sebelum kita dilahirkan.”
“Jika demikian halnya, mengapa kita tidak bertemu sebagai pengusaha tambang sukses dan seorang pemimpin partai?”
Tipang Pakuban, pria berpipi tirus itu memang belum lama berkenalan dengan Siwat. Pertemanan mereka terjalin saat Siwat ditugaskan untuk mengurus konflik lahan yang terjadi di suatu daerah di bagian tenggara pulau. Singkat cerita, ketika sedang membeli sebungkus rokok di warung yang mesti ditempuh sejauh dua kilometer, Siwat disapa oleh Tipang yang baru saja pulang dari ladang. Tipang adalah seorang petani jagung yang hendak disingkirkan dari tanahnya.
Tak hanya jagung, Tipang dan petani lain juga sering kali menanam beraneka tanaman hortikultura berupa sayur-mayur untuk menebalkan pundi-pundi seperti jagung, kelapa, pisang, hingga buah naga yang selanjutnya mereka pasok ke pasar yang berpopulasi padat. Namun demikian, usaha-usaha itu tampak makin mengkhawatirkan mengingat adanya megaproyek nasional yang hendak menyulap tanah kelahiran Tipang menjadi kawasan industri, perdagangan, dan wisata sekaligus.
Lain halnya dengan Siwat Sinoka. Pemuda itu tumbuh dan dibesarkan di keluarga kaya raya, sesuatu yang ia sembunyikan dari orang-orang, tak terkecuali Tipang. Siwat lahir pada 1996 di bilangan Menteng. Ayahnya merupakan seorang konglomerat yang sempat menjadi tangan kanan jenderal tentara lalu mendirikan perusahaannya sendiri, yang saat ini telah menggurita ke sejumlah sektor, setelah kerusuhan 1998. Sedangkan ibunya, perempuan langsing berzodiak Gemini, adalah pejabat tinggi provinsi yang telah berkarier selama lebih dari dua dekade.
Waktu terus bergulir tanpa ada yang dapat menghentikan. Siwat beranjak dewasa dan melaksanakan wisuda kampus di benua seberang yang semestinya ia hadiri dua tahun lebih dini. Sebagai hadiah kelulusan, ayahnya menawarkan salah satu perusahaan mapan kepunyaannya di bidang pertambangan untuk dikelola. Akan tetapi, Siwat lekas-lekas menolak dan memilih pergi dari rumah untuk merintis profesi sebagai advokat.
Siwat secara gamblang beralasan bahwa berkarier di pertambangan, ditambah akses penuh yang ditunjang oleh relasi ayahnya, akan membuat dirinya rapuh dan berjarak dari hal-hal yang ia harapkan selama ini: membuka beberapa perpustakaan umum skala menengah dengan arsitektur estetis berbahan mahoni yang tersebar di sejumlah desa korban gusuran. Dan idenya itu, dalam banyak hal, pun merunyamkan keluarga besarnya di Kalimantan.
Satu hal yang membuat Siwat betah berlama-lama dengan Tipang adalah sifat dan perilaku si petani yang arif. Umur Siwat dan Tipang terpaut dua puluh satu tahun. Oleh sebab itu, ia sebisa mungkin menyimak kisah apa pun yang disemburkan oleh Tipang, dari yang mampu ditelan nalar hingga yang tidak. Mengobrol dengan Tipang seakan membuat Siwat merasakan kembali ruang kelas filsafat Pittsburgh yang dikenyamnya dulu di Pennsylvania. Sudah lewat dua jam, dan Siwat masih bertumpu di posisinya semula. Dalam benaknya, pemuda itu bersusah payah mencermati tiap kata yang keluar dari mulut Tipang.
“Ingat ini,” sambung Tipang lagi seraya menyesap tetesan terakhir es jeruk perasnya, “manusia memang tidak dapat menentukan takdirnya sendiri. Pasalnya, usaha manusia itu saja sudah bagian dari takdir. Yang jelas, Tuhan senantiasa memberi nikmat dan ini akan terjadi terus hingga kemudian kita sendirilah yang mengubah keadaan dengan beragam maksiat. Nah, ketika manusia telah bermaksiat, maka nikmat itu akan diubah menjadi musibah.”
“Hmmm.”
“Maksudku begini, Wat…. Di saat sebagian manusia memutuskan untuk bekerja pada kerusakan ruang hidup, sebagian yang lain justru mengambil jalan yang berlawanan, rute yang lebih sukar untuk diarungi. Toh bukankah itu gambaran sederhana atas kehidupan?”
Siwat hanya memandangi sarung berpola kotak yang melintang di bahu kawannya sepintas lalu. Ia hampir kehabisan kata-kata, lantas mencoba mencarinya di sekitar jendela warung, di mana deretan kaca nako usang memantulkan sinar matahari yang cerah. Tapi upayanya gagal.
“Yah, seperti aku ini, misalnya,” lanjut lelaki kurus itu sambil terkekeh, “janin bernama Tipang Pakuban ini sesungguhnya telah digariskan menjadi seorang pemimpin partai pemenang pemilu.”
“Ah, jika cara mainnya memang seperti itu, betapa mudahnya menjalani hidup sialan ini,” Siwat menanggapi sambil mengayunkan kepalanya dengan gerakan lambat tanda hilang akal.
“Nah, maka dari itu manusia ditakdirkan untuk lupa. Apa kamu lupa bahwa rakyat jelata macam aku ini adalah penggerak utama mesin partai? Kamu sekolah, kan?” sahut Tipang tanpa pikir panjang.
Tipang terhenyak ketika menyadari nada bicaranya yang meninggi. Ia berusaha menguasai keadaan. Pria gemuk dengan cambang lebat itu memejamkan matanya, lalu menghela napas. Sayup-sayup didengarnya sirene dan lantunan ayat suci dari pengeras suara langgar di kejauhan. Berikutnya, Tipang memilah kata demi kata untuk menutup percakapan itu.
“Agar adil, manusia sengaja dibiarkan lupa, mungkin semacam kutukan? Entahlah. Yang pasti, derajat manusia bisa menjulang ke langit dan terjun ke dasar bumi, semuanya sesuai dengan pilihannya yang dilandasi oleh akal dan nurani.”
Tak lama berselang, Tipang lantas berdiri dan meraih gelasnya untuk dikembalikan ke warung makan tempat ia memesan. Pada detik yang bersamaan, ia memperhatikan Siwat yang sedang berkutat dengan carut-marut yang berputar di otaknya, meninggalkan kerutan di area dahinya.
“Coba tengok alat-alat berat itu,” Tipang mengarahkan telunjuknya, tepat ke arah sebuah wilayah perkampungan, “aku mungkin memang sudah ditakdirkan untuk digusur paksa, siapa yang tahu?”
“Maksudmu, para pengusaha yang bersekongkol orang-orang partai itu, yang hendak menggusur perkampungan ini juga sudah ditanya sebanyak tujuh puluh tujuh kali oleh malaikat?”
Si petani menyeka keringat di dadanya. Melihat ada kesempatan, Siwat segera melancarkan argumennya. Siwat berkata, ada satu sistem yang membuat segelintir manusia sanggup mengakali takdirnya sendiri dan orang lain, dan melahirkan candu seolah-olah itu semua bagian dari takdir. Untuk itu, tambah Siwat lagi, harus ada sekelompok manusia yang rela memperjuangkan nasib sesama demi menghalau jeratan sistem tersebut.
“Wat, kamu masih muda, siapa yang tahu kamu bakal jadi pengusaha tambang? Aku saja urung mengetahui soal latar belakangmu. Intinya, kita boleh saja lupa akan tujuh puluh tujuh pertanyaan yang dilontarkan kepada kita saat masih berupa janin berusia empat bulan, namun pada akhirnya kita berdua nyatanya sama-sama ditakdirkan untuk bertemu di sini, di bawah pohon ara ini.”
“Jadi, menurutmu, menjadi pelupa termasuk kesepakatan yang kita setujui di alam sana?”
“Barangkali memang seperti itu? Toh kita sama-sama lupa.”
Sejurus kemudian, kehampaan menggantung di sekeliling mereka. Alih-alih menyinambungkan ocehannya yang melelahkan itu, Tipang justru menepuk pundak Siwat yang baru saja mematikan rokoknya dengan kekesalan yang bersemi di sekujur dada.
“Mustahil mengingat seluruh pertanyaaan dan persetujuan kita ketika di dalam kandungan,” tegas Tipang, “sebab bagaimanapun, alam semesta memang dibangun oleh miliaran rahasia.”
Depok – Ciputat / September – Oktober 2024.
Penulis, Muhammad Faisal Akbar
Akun Media Sosial: Instagram (@icalbar)
Biodata Singkat: Muhammad Faisal Akbar lahir di Jakarta dan bermukim di Depok. Pengagum sastra dan sepak bola indah ini menulis esai dan cerpen di sejumlah media sejak tahun 2023.
- BUKA TAHUN 2026, BAND STEVUNK DARI PADANG RILIS DUA LAGU BERNUANSA PROTES! - 23 Januari 2026
- PELESIRAN – Sebuah Catatan: Setelah UWRF, Apalagi yang Kau Cari? | Hasbunallah Haris - 10 Januari 2026
- Resensi: Antara Kota dan Kampung, Pecundang di Negeri Orang, dan Narator yang Berpetuah | Dandri Hendika - 8 Januari 2026


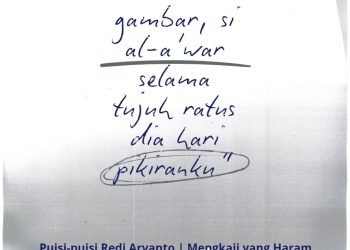




Discussion about this post