
Dengung Tanah Goyah adalah karya sastra ke-sepuluh Iyut Fitra. Buku ini diterbitkan oleh JBS pada Agustus 2024 dengan tebal 100 halaman. Terdapat 41 buah puisi di dalamnya. Raudal Tanjung Banua, sastrawan Indonesia yang banyak menulis puisi dan cerpen, memberikan prolog bagi buku ini. Sementara itu, epilog-nya diberikan oleh Kiki Sulistyo, sastrawan Indonesia yang bertekun di Komunitas Akarpohon, yang fokus pada kerja penciptaan, diskusi dan dokumentasi sastra, serta proyek-proyek kesenian yang lain.
Saya memilih tiga puisi dalam kumpulan ini untuk dibahas. Pertimbangannya, mereka, saya rasa, sudah mewakili gagasan umum Iyut Fitra yang ingin disampaikan lewat buku ini. Puisi-puisi itu adalah “Tanah Goyah”, “Negeri Berpagar Rimbun”, dan “Negeri Tanpa Bendera”.
Kita mulai dengan “Tanah Goyah”.
Apa yang Iyut Fitra maksud dengan frase ‘tanah goyah’? Menurut hemat saya, tanah goyah melambangkan suatu ketidakstabilan kehidupan. Apakah yang membuat kehidupan itu dirasakan tidak stabil? Ialah ‘kabut asap dan udara hitam’.
Apabila kita bergerak ke luar dari teks puisi ini, maka kita akan menemukan fakta bahwa kebakaran hutan dan lahan meningkat drastis pada Juli hingga Agustus 2024 di wilayah-wilayah Indonesia. Sejak Juni hingga Juli 2024, luas area yang terbakar melonjak dari 11.711 hektar menjadi 60.292 hektar. Ada 34 ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi yang ikut terbakar sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024 (Madani, 2024).
Selain ‘kabut hitam’, ketidakstabilan juga dirasakan karena ‘tanah asal tinggal nama’. ‘Tanah asal’ adalah simbol dari akar budaya. Maka, ketika ‘tanah asal’ itu tiada, budaya juga ikut hilang. Demikian pula identitas.
Hilangnya tanah asal, membuat ‘tokoh ia’ menjadi seperti ‘burung yang mencari tempat hinggap’. Ketiadaan ‘tempat hinggap’ ini menganalogikan masyarakat yang terusir dari kampung halamannya sendiri, dari tanah leluhurnya. Tidak punya kuasa atas hak miliknya, bahkan hanya untuk tinggal menetap. Hal ini bisa dikontekstualisasikan kepada kondisi masyarakat adat saat ini.
Sebagai dampak tidak adanya undang-undang tentang masyarakat adat, banyak hal sudah menimpa mereka. Proyek Ibu Kota Nusantara, menurut Sri Endah Kinasih, pakar Antropologi Hukum Unair, akan menghilangkan 21 etnis beserta flora fauna dan tradisi berbasis ekologi yang mereka miliki. Konflik agraria lainnya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Penderitaan Suku Anak Dalam 113 di Sumatra; protes masyarakat Kasepuhan di Jawa Barat; kesedihan masyarakat adat Desa Punan Dulau di Kalimantan Utara; nestapa komunitas Adat Karunsi’e di Sulawesi; dan dukacita banyak masyarakat adat lainnya tercatat dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Komnas HAM RI pada 2016.
Peminggiran masyarakat adat seiring dengan dipinggirkannya kearifan lokal dalam pembangunan Indonesia. ‘Bah lapar yang bergulung’ adalah arus budaya asing tak terbendung yang menghancurkan kebudayaan lokal sehingga kebudayaan itu menjadi ‘ungguk puing bertimbun basah’. Ini adalah penyebab ketidakstabilan yang lain. Untuk hal ini, adat Minangkabau mengisyaratkannya dalam pepatah berikut.
Sakali aie gadang sakali tapian baralieh
Namun tidak di lua patuik
Hilang pulau tinggalam padang
Aie nan janieh nan disauak
……
Dek manuruik aliran jaman
Hanyuik di maso tak mambeso
Runtuah budi lah caie iman
Manyimpang di adat jo agamo
(Sekali air besar, sekali tepian berubah
Tapi tidak di luar patut
Hilang pulau, tenggelam padang
Air jernih yang diambil
…
Karena mengikuti aliran zaman
Hanyut di masa tak membeda
Runtuh budi, hancur iman
Menyimpang dalam adat dan agama)
Sebagaimana yang Iyut Fitra ibaratkan pula dalam kumpulan puisi Baromban (2016): ‘layang-layang berekor panjang/ layang-layang bergoyang-goyang/ bila putus, ia tak akan lagi pulang’. Layang-layang adalah simbol dari manusia yang masuk ke persilangan angin peradaban dunia. Ia akan meliuk-liuk indah jika talinya masih dipegang erat dari bawah. Akan tetapi, apabila talinya putus, maka ia akan terombang-ambing tak tentu arah. Tali itu adalah keterikatannya kepada akar budaya.
Kita beralih kepada puisi ke-dua: “Negeri Berpagar Rimbun”.
Frase ‘negeri berpagar rimbun’ dapat dibaca sebagai tanah tempat tinggal yang dikelilingi pohon-pohon yang berdaun dan bercabang banyak. Apakah yang dimaksudkan Iyut Fitra dengan itu? Menurut tafsir saya, tanah tempat tinggal yang diangankan oleh ‘tokoh ia’ adalah tanah yang subur, yang mendukung keberlangsungan alam.
Ekosistem alami sesungguhnya memberikan kepada kita jasa-jasa yang dikenal sebagai ‘ecosystem services (jasa ekosistem)’. Ekosistem mampu memberi kita makanan, udara bersih, dan bahan bakar; mampu mengatur proses ekologisnya sendiri; mampu menyediakan kesempatan bagi aktivitas spiritual-inspirasional, edukasi, dan rekreasi kita; serta mampu melangsungkan proses pada dirinya sendiri untuk menghasilkan ketiga jasa sebelumnya. (Costanza, 1997: 253-260).
Akan tetapi, ada ‘simpang-simpang membelintang’ yang membuat sulit terwujudnya negeri yang diidamkan itu. Aktivitas manusia modern, seperti deforestasi, urbanisasi, perluasan pertanian, dan penggunaan bahan bakar fosil mengganggu stabilitas ekosistem natural (Environment Department, 2009).
Di samping itu, kini, di Indonesia terdapat disrupsi digital, menurunnya kesejahteraan ekonomi rakyat, dan merosotnya mutu demokrasi. Semua itu berujung pada krisis politik. Dunia kini yang volatile (tidak stabil), uncertain (tidak pasti), complex (rumit), dan ambiguous (ambigu) adalah simpang-simpang yang lain.
‘Negeri berpagar rimbun’ itu entah di mana. Yang ada kini hanya ‘musibah dan bencana’ dan ‘lagu perang demi segala kuasa’. Dalam rentang 1 Januari sampai 7 Oktober 2023, BNPB mencatat 3.089 bencana, 898 berupa banjir dan 862 cuaca ekstrem. Ada 707 karhutla, 451 tanah longsor, 121 kekeringan, 24 abrasi dan gelombang pasang, 24 gempa bumi, dan 2 erupsi gunung api. Terdapat 205 korban meninggal dunia, 10 jiwa hilang, 5.555 jiwa luka-luka dan terdampak, serta 5.459.935 jiwa mengungsi (Tempo, 2023).
Melihat kondisi ini, tokoh ia mengeluarkan ‘pekik damai yang tak sampai-sampai’. ‘Tak sampai-sampai’ artinya tidak dipertimbangkan oleh sturuktur sosial dominan. Menurut filsuf Prancis, Jacques Ranciere, yang banyak berbicara tentang politik, ‘pekik damai’ tidak sia-sia. Pada saat pekik itu mengganggu tatanan dominan, terjadilah apa yang disebut Ranciere dengan ‘demokrasi’ (Ranciere, 2000).
Puisi terakhir adalah ‘Negeri Tanpa Bendera’.
Kata ‘bendera’ dipilih Iyut Fitra untuk mengungkapkan pikirannya. ‘Negeri tanpa bendera’ adalah negara yang tidak lagi memiliki identitas dan nilai-nilai nasional. Rakyatnya seperti ‘unta-unta gurun’ yang hanya melihat ‘fatamorgana’. Mereka hanya melihat ‘pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur’ yang semu.
Faktanya, Indonesia merupakan negara ke-empat dengan ketimpangan tertinggi di dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand (Tempo, 2024). Di samping itu, jumlah penduduk miskin Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juli 2024 adalah 25,22 juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara korup dunia. Indeks Persepsi Korupsi 2022 memperlihatkan bahwa Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
Dari segi keadilan, Survei Pandangan Masyarakat terhadap Hak Memperoleh Keadilan di Indonesia menunjukkan bahwa 27,8 persen responden pernah mengalami, mendengar, atau menyaksikan diskriminasi oleh aparat penegak hukum (Kompas, 2021). Dilihat dari sisi persatuan, Indonesia memiliki banyak politik berunsur SARA, khususnya saat pemilihan pemimpin (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2020). Indonesia juga belum sepenuhnya berdaulat. Investasi asing cukup dominan menguasai sektor- sektor strategis perekonomian Indonesia (Kompas, 2011).
Akan tetapi, sebagian rakyat tidak putus asa. Mereka senantiasa berjuang ‘ke barat’, ‘ke arah matahari’. Apa yang dimaksud dengan ‘barat’? Barat adalah tempat matahari terbenam yang menunjukkan akhir hari. Apabila hari ini memiliki banyak kesalahan, maka esok adalah kesempatan baru untuk menimbunnya dengan kebaikan yang lebih banyak. Oleh karena itu, barat adalah simbol perubahan.
Dengan negeri yang ‘damai serupa telaga’, perubahan dimungkinkan. Telaga adalah lambang dari kedalaman dan kebijaksanaan. Indonesia, sesungguhnya, tidak berkekurangan dalam kebijaksanaan hidup. Dalam budaya Minangkabau, misalnya, ada yang dinamakan Kato Adat nan Limo yang berujung pada keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat Minangkabau. Ada pula petatah-petitih yang menunjukkan cara berlaku kepada alam. Salah satunya, tampak dalam petuah berikut.
elok-elok mamaliharo isi alam
elok-elok mamaliharo anak kemenakan
karano lauik indak panuah di aie
bumi indak panuah dek tumbuah-tumbuahan
jan lah mamakan manghabihkan
jan lah manabang marabahkan
jan lah mamancuang mamutuihkan
(baik-baik memelihara isi alam
baik-baik memelihara anak dan kemenakan
karena laut tidak penuh oleh air
bumi tidak penuh oleh tumbuh-tumbuhan
janganlah memakan dengan menghabiskan
janganlah menebang dengan merebahkan
janganlah memancung dengan memutuskan)
Dalam khasanah kebudayaan Jawa, dikenal jagad alit (manusia) dan jagad agung (alam). Sementara itu, dalam cerita rakyat Bugis, alam tidak hanya berfungsi sebagai latar, tetapi juga tokoh yang aktif mempengaruhi keputusan dan takdir tokoh-tokoh lain. Hutan, sungai, dan fenomena cuaca menjadi simbol yang merefleksikan gambaran emosional dan moral serta menekankan pentingnya hubungan yang baik antara manusia dan lingkungannya. Demikian pula dalam kebudayaan-kebudayaan lain di Indonesia.
‘Telaga’ itu adalah modal yang besar dalam membangun bangsa ketimbang memaksakan mengambil cara pandang barat, sisa penjajahan, yang membuat bangsa senantiasa tertinggal karena memang tidak sesuai dengan jati dirinya. Dengan frase ini, Iyut Fitra menyuarakan untuk kembali merujuk kepada kearifan lokal dan akar budaya bangsa. ‘Ke hulu’, tutur Iyut Fitra, dalam kumpulan puisi terdahulunya, Baromban (2016).
Dengan modal besar ini, para pejuang itu ‘berbondong menuju awan’. Apakah yang Iyut Fitra maksud dengan ‘awan’? Awan melambangkan harapan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 43:
Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya…
Maka, mereka yang berbondong-bondong dengan membawa luka itu, pada waktunya, akan menjadi hujan yang menyuburkan negerinya yang tandus.
Demikianlah, melalui pendekatan semiotika yang saya lakukan kepada ketiga puisi pilihan ini, kita dapat melihat bahwa isu utama yang disoroti Iyut Fitra dalam Dengung Tanah Goyah adalah kenegaraan, lingkungan, dan kearifan lokal. Isu kenegaraan tampak dari kosakata ‘tanah’, ‘negeri’, dan ‘bendera’. Di dalamnya, terkandung kesedihan dan harapan atas Indonesia. Lahirnya kesedihan disebabkan kondisi Indonesia pada tahun-tahun terakhir amat buruk. Lahirnya harapan disebabkan Indonesia sesungguhnya masih memiliki modal besar, dari kebijaksanaan budayanya, untuk bangkit dan menjadi negara besar.
Isu lingkungan terindikasi dari penggunaan kosakata ‘rimbun’, ‘pohon’, ‘embun’, ‘burung’, dan ‘udara hitam’. Isu ini paling banyak ditekankan dalam menggambarkan kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Lingkungan yang rusak adalah sumber malapetaka yang banyak menimpa masayarakat Indonesia saat ini.
Sementara itu, isu kearifan lokal direpresentasikan oleh kata-kata ‘tanah asal’, ‘pantun’, dan ‘pepatah’. Melalui isu ini, Iyut Fitra menyampaikan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat ditinggalkannya kebijaksanaan Nusantara yang sarat khasanah harmonisasi antara manusia dan alam.
Sehla Rizqa Ramadhona lahir di Payakumbuh, 24 Januari 1996. Ia menamatkan pendidikan S-1 Sastra Indonesia di Universitas Jenderal Soedirman pada 2018. Pendidikan masternya ditamatkan di Magister Sastra Universitas Gadjah Mada pada 2021. Beberapa tulisannya ialah Analisis Tematik atas Kumpulan Puisi Baromban Karya Iyut Fitra (2018), A Discursive Strategy to Maintain Cultural Islam-Political Islam Power Relation in Indonesia in Triwikromo’s “Lengtu Lengmua” (2021), Posisi Perempuan dalam Lembaga Pernikahan pada Novel Ginko Karya Watanabe Jun’ichi (2021), dan Hantu Padang: Sastra Perjalanan dan Ulang-Alik Identitas (2024). Saat ini, ia bekerja sebagai Dosen Sastra Minangkabau Universitas Andalas.
- BUKA TAHUN 2026, BAND STEVUNK DARI PADANG RILIS DUA LAGU BERNUANSA PROTES! - 23 Januari 2026
- PELESIRAN – Sebuah Catatan: Setelah UWRF, Apalagi yang Kau Cari? | Hasbunallah Haris - 10 Januari 2026
- Resensi: Antara Kota dan Kampung, Pecundang di Negeri Orang, dan Narator yang Berpetuah | Dandri Hendika - 8 Januari 2026

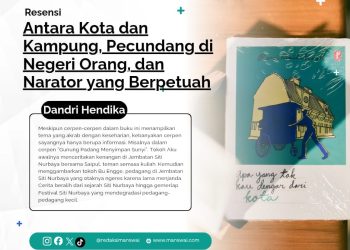
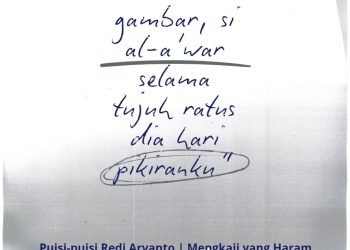
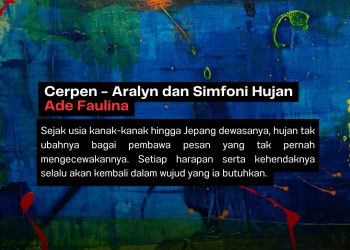
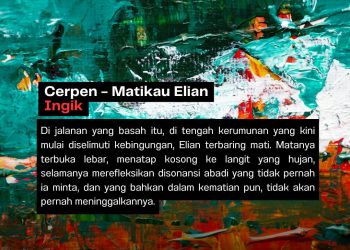


Discussion about this post