
Kapiturunan
Marsiah menambahkan beberapa potong kayu ke dalam tungku, lalu memungut talang yang tergeletak di samping tungkahan yang ia duduki. Whooosh… Seketika Marsiah menarik mundur kepalanya. Asap dan debu menyerbu wajahnya saat meniup talang untuk memperbesar nyala api tungku. Rupanya ada butiran-butiran debu yang masuk ke matanya.
Rasanya hampir satu purnama Angku Sabir tergeletak sakit. Angku yang dulunya amat disegani atau lebih tepatnya ditakuti, bukan saja oleh kami keluarganya tapi juga orang-orang sekampung. Namun sekarang terlihat lunglai dan tak berdaya. Setiap batuk, maka darah kental menyembur dari mulut dan hidungnya. Badan yang dulu tegap berisi, kini kurus dengan tulang-tulang yang menonjol.
Namun herannya beliau selalu menolak bila diajak berobat, baik itu ke dukun kampung maupun mantri atau dokter. Bukan karena tidak punya uang, sebab sebagai pensiunan kepala sipir penjara dan penghulu, Angku Sabir dan keluarganya adalah orang yang cukup berada dan terpandang di kampung ini. Beliau hanya minta disediakan batu es untuk meredakan sakit dan panas di dadanya setiap beliau batuk darah. Bahkan Etek As, anak kesayangan Angku Sabir tak mampu membujuknya untuk berobat. “Kalau kalian merasa susah merawatku, ya, sudah kau dan saudara-sadaramu lempar saja aku ke laut. Habis perkara. Sakitku ini adalah buah dari jalan hidup yang kupilih, dan siksa ini harus kutanggung sampai nafas terakhirku, itu tak lama lagi”, itu kalimat yang keluar dari mulut Angku Sabir.
Aku adalah jalan mautmu
Tapi dosamu bukanlah dosaku, tidak juga salahku
Keinginanmu jadi keinginanku
Hasratmu jadi hasratku
Aku, hanyalah angin yang bersiul di telingamu
Dan selimut dingin yang merangkup kudukmu
“Siah, tolong kau jerangkan air seperiuk! Kalau sudah mendidih nanti, sisakan sedikit buat mandi Angkumu. Etek dan Amakmu keluar sebentar beli batu es”, pesan Etek As sambil berbalik menaiki tangga kayu menuju langkan terus ke pintu depan. Itulah akhirnya, Marsiah terperangkap di dapur tak berani beranjak. Jangankan untuk naik ke langkan tengah tempat Angku Sabir tergeletak, melirik pun ia tak berani. Maklumlah Marsiah dan cucu-cucu Angku Sabir yang lain pun sangat takut pada beliau terutama pada tatapan matanya yang tajam dan terkesan bengis. Bisa kencing di celana kalau berhadapan langsung dengan beliau.
Sembari menunggu airnya mendidih, dalam hatinya Marsiah membatin, kenapa Amak bawa dia kemari?. Biasanya Amak juga perginya sendiri tak pernah mengajak anak-anaknya. Dan kenapa pula dia (Marsiah) yang diajak, kan ada kak Fatimah, atau kak Saur. Padahal pekerjaan Marsiah di rumah juga belum kelar. Kuda-kuda (penarik bendi) belum dimandikan dan dikasih makan. Bisa-bisa pulangnya Apak (Bapak) bakal kasih hukuman tidur di kandang kuda semalaman. ”Huukh, huukh”, suara batuk Angku Sabir membuyarkan lamunan Marsiah, agak takut-takut ia sedikit menoleh ke langkan tengah. Terlihat angku Sabir berusaha mengangkat kepala dan dadanya. Dengan susah payah dan sisa-sisa tenaganya, “as, asss, mana kau,… Aasss”, lenguhnya.
Termangu sesaat, Marsiah bangkit berjalan hendak ke langkan tengah, namun baru satu dua langkah ia berhenti. Hatinya bimbang, dia ingin mendekat tapi takut menggerogoti hatinya. Pada akhirnya dia berbalik memutuskan untuk kembali duduk di depan tungku, rasa takut membuat keberaniannya ciut. “AASSS, “ Marsiah terkesiap. Bukan lenguhan, tapi sebuah teriakan, entah bagaimana suara angku Sabir yang begitu lemah bisa sekeras itu. Namun cukup membuat Marsiah terlonjak, secara naluriah berlari menghampiri angku Sabir. Marsiah sedikit berjongkok di samping angku Sabir. Muntahan darah segar memenuhi dada dan sebagian wajah beliau.
“Ngku.., “ hanya itu ucapan yang keluar dari mulut Marsiah. Tiba-tiba saja tangan angku Sabir menjambak kepalanya dan menarik wajahnya mendekat, sangat dekat malah. Mata angku Sabir membelalak, pandangan Marsiah langsung berhadapan dengan mata angku Sabir. Kalau hari-hari biasa, bisa kecing di celana bila bertatap langsung dengan beliau, maka kali ini nyawa Marsiah serasa terbang entah ke mana. Walau hanya beberapa saat saja, tapi bagi Marsiah terasa sangat-sangat lama. “Duarr,” tak ada mendung siang itu, apalagi hujan tapi petir terdengar begitu kerasnya. Petir di siang terik yang panas. Petir yang menyelamatkan kepala Marsiah dari cengkraman tangan angku Sabir.
Dia terjungkang, pandangannya gelap, dunianya terasa menjauh dan semakin jauh. Dalam sisa-sisa kesadarannya terdengar langkah-langkah samar kemudian hilang. Entah berapa lama, saat sadar Marsiah menemukan dirinya di atas palanta panjang di dapur. Dia duduk dan berusaha mengingat apa yang telah terjadi padanya. Dia bingung.
Hari ini adalah hari dimana engkau dan aku satu
Tidak satu masa pun yang kau lewatkan tanpa aku
Hingga dekat pada ajalmu, kau akan tahu.
Sejak hari itu dan hari-hari berikutnya, Marsiah bukan lagi Marsiah yang sebelumnya. Marsiah, gadis remaja berumur 14 tahun yang bersama tiga saudara lelakinya terpaksa harus putus sekolah di kelas 3 karena setelah bapaknya meninggal dan amak menikah lagi dengan Apak (suami ketiga amak) seorang bujang anak tuan tanah di kampungnya. Marsiah yang dengan saudara-saudaranya ditugasi mengurusi kuda-kuda bendi apak, tak jarang pula cemeti pelecut kuda pun dilecutkan ke mereka.
Sore beranjak, petang menjelang. Siluet kemerahan tampak mulai membias di ufuk barat mengantar matahari terbenam. Sebagai tanda bagi orang- orang untuk pulang melepaskan penat bersama keluarga setelah seharian mencari nafkah. Senja di kampung ini terasa tentram, ditemani lantunan suara mengaji dari surau, semakin menenangkan hati. “Siah! Siah!… Oi Siah! Keluar kau Siah!“ terdengar teriakan dari halaman rumah, memecah keheningan. Amak keluar dari rumah, “Oo, rupanya kamu Pia, ada apa kau panggil-panggil Siah. Masuklah dulu, kita bicara di dalam!“ Dari depan pintu amak dapat melihat Pia yang sedang marah bersama Erwin putranya. “Mana Siah anakmu? Biar kutempeleng seperti dia menempeleng anakku. Kau lihat pipinya bengkak lebam kan?” Pia semakin emosi.
“Di situ kau rupanya, awak kau, ya!“ Pia segera menyongsong Marsiah yang baru saja keluar dari kandang kuda di samping rumah. Tangan terangkat tinggi, sekuat tenaga diayunkan hendak menampar Marsiah. Kalau kena, pastilah Marsiah bakal tersungkur dibuatnya. Namun itu tak pernah terjadi. Tangan Pia tertahan di udara, sesaat kemudian tubuhnya gemetar. Marsiah menatap tajam, “bukan aku yang salah, tapi anakmu yang menggangguku”, jawabnya dingin. Pia berbalik, tergesa-gesa menarik Erwin yang masih meringis memegang pipinya yang bengkak membiru. Sekilas Amak melihat bagaimana ketakutannya wajah Pia tadi.
Amak tidak percaya, heran bagaimana mungkin Marsiah melukai Erwin anak yang lebih tua 3 tahun darinya, Laki-laki pula. Amak melangkah mendekati Marsiah. Sekilas amak mencium aroma bunga melati. “Dia mengolok-olokku, Mak. Bauku seperti bau kuda katanya. Jadi kutampar dia”, Marsiah menjawab. Tanpa dijelaskan Marsiah pun, Amak sebenarnya sudah mengerti permasalahannya. Erwin memang anak yang agak bandel, mungkin karena badannya yang lebih besar dari anak-anak seumurannya sehingga dia jadi semena-mena terhadap teman-temannya. Amak memperhatikan Marsiah dengan seksama, ”apa di mulutmu, Siah! Sejak kapan kau suka dengan bunga melati?“ tanya Amak.
Keheranan amak berlanjut keesokan harinya. Suami Pia datang mencari Marsiah. Awalnya Amak berfikir bahwasanya masalah semalam akan berkepanjangan. Ternyata suami Pia datang meminta Marsiah menyembuhkan Pia. Beliau bercerita bahwa sejak pulang semalam Pia mengalami demam, badannya panas. “Kami sudah panggil pak mantri, diperiksa dan diberi obat demam. Tapi panasnya tidak turun-turun”, jelas beliau. Tidurpun Pia mengigau seperti ketakutan. Pia sering memanggil-manggil Marsiah saat ia mengigau. Marsiah mengambil segelas air putih, meniupnya pelan dan panjang. “Minumkan air ini ke etek, sisakan sedikit buat dicampurkan ke air mandinya! Erwin bagaimana, Pak? Pipinya?“
”Semalam sudah diolesi salep yang diberikan pak mantri, syukurlah pagi ini bengkaknya sudah menyusut”, jawab suami Pia sambil menerima air yang diberikan Marsiah.
Namanya kampung, kejadian apapun cepat menyebar. Marsiah yang mengobati orang sakit, Marsiah yang tangan kirinya berbisa, bahkan beberapa cerita menyebar sudah dilebih-lebihkan. Namun ada untungnya juga bagi Marsiah, tak jarang orang-orang memberinya sedikit uang jajan setelah mengobati kerabat mereka yang “tasapo” (kesambet). Kawan-kawan Marsiah pun agak segan mengganggunya. Mereka segera terdiam bahkan menjauh bila Marsiah sudah menatap tajam mereka, takut Marsiah tersinggung.
Marsiah tidak tahu, ini kutukan atau berkah bagi dirinya. Mungkinkah dia mewarisi kepandaian angku Sabir. Dalam kesendiriannya Marsiah tidak lagi benar-benar sendiri. Semuanya berawal pada malam setelah beberapa hari angku Sabir meninggal. Kuda-kuda di kandang meringkik bahkan terdengar seperti menendang-nendang. Takut Apak dan Amak terbangun, Marsiah bersama Mardi adiknya keluar lewat pintu belakang. Dan di sana mereka melihatnya. Sosok besar, hitam, dan tinggi. Seluruh tubuhnya dipenuhi rambut kasar. Ketakutan Mardi segera berlari balik ke dalam rumah. Tapi tidak dengan Marsiah. Dia mematung, berhadap-hadapan, seperti ada ikatan yang tak ia mengerti dengan makhluk itu. Tidak ada kata, tidak ada perintah, dalam hatinya berujar, “pergilah!“ Makhluk itupun hilang. Malampun kembali hening, kuda-kuda kembali tenang.
Penulis, Risnandar Tjia. Ia adalah seorang Teknisi Ahli Reparator. Selain itu ia menyukai—mempelajari ilmu tafsir dan dunia metafisika, beliau juga terlibat dalam banyak project kreatif; film, budaya, dan sastra lisan.
- Cerpen Kapiturunan – Risnandar Tjia - 8 Februari 2026
- Ke Rumah Nan Tumpah #10: Pameran Silotigo “Rukun Paksa/ Berakit-rakit ke Hulu Tinggal di Genangan” dan dan Gelar Karya Kelana Akhir Pekan - 5 Februari 2026
- SERI – AJI MANTROLOT| Penggalan X: KABAU GADANG (Bagian VIII) | Dewang Kara Sutowano - 3 Februari 2026



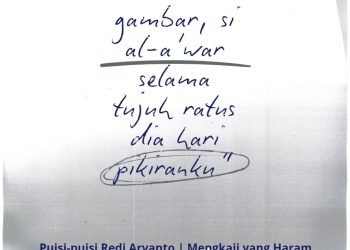

Discussion about this post