
Antara Kota dan Kampung, Pecundang di Negeri Orang, dan Narator yang Berpetuah
Judul : Apa yang Tak Kau Dengar dari Kota
Pengarang : Rori Maidi Rusji
Penerbit : Purata Publishing
Tahun Terbit : 2025
Tebal : 158 Halaman
Selalu ada kebanggaan ketika orang dari kampung pulang dari kota. Orang kampung selalu ingin menceritakan wisata-wisata yang dikunjungi selama di kota dan membangga-banggakan oleh-oleh khas kota. Kota dan kampung seringkali diperbandingkan karena mewakilkan sifat yang bertolakbelakang; ramai dan sepi, maju dan tertinggal, canggih dan tradisional. Namun, apa yang terlihat glamour dari kota tak melulu lebih baik dari udiknya kampung. Beragam fenomena-fenomena unik di kampung tak kalah menarik dengan kota.
Hal inilah yang ditampilkan dalam kumpulan cerpen Apa yang Tak Kau Dengar dari Kota. Cerpen-cerpen dalam buku ini coba merangkum sisi kehidupan kota dan kampung. Permasalahan-permasalahan di kota tempat kita tinggal, maupun kampung halaman yang kita tinggalkan, terasa dekat karena sering dijumpai. Permasalahan seperti kegagalan di rantau, kemiskinan, perselingkuhan, pemalakan di pasar, anak kos hidup susah, atau mahasiswa akhir belum wisuda, adalah isu-isu yang disajikan.
Kampung yang seringkali berkaitan dengan ketertinggalan, terasing, dan minim fasilitas, justru menyediakan hal-hal yang tidak dimiliki kota. Kota bergerak cepat, sibuk, dan menjemukan, menjadikan individunya egois dan melupakan sisi komunal. Sedangkan kampung, yang bergerak pelan pada ruang sempit, menciptakan individu-individu solid. Dalam cerpen “Sore yang Merah”, terlihat bahwa masyarakat kampung saling bantu jika dihadapkan pada suatu masalah. Pedagang-pedagang di pasar rela berkelahi dengan preman demi melindungi pedagang lain dari pemalakan. Meski sama-sama bertujuan mencari uang, hubungan antar pedagang bukanlah kompetitor. Mereka saling terhubung dan rela berkorban apa saja, sekalipun itu nyawa.
Kampung dengan segala “keterbatasan”, memaksa orang-orangnya pindah ke kota, atau seringkali disebut merantau. Cerpen “Apa yang Tak Kau Dengar dari Kota” memperlihatkan bahwa merantau merupakan tuntutan karena ketidakberpihakan nasib di kampung. Merantau bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan pencarian destinasi demi memperbaiki kondisi ekonomi.
Namun, merantau tak punya jaminan sukses. Dalam cerpen ini, para perantau tidak melulu pulang seperti yang diharapkan; mengendarai mobil baru atau dipenuhi perhiasan sekujur badan. Merantau seringkali bukanlah solusi, dan kampung—dengan segala keterbatasan—pada akhirnya tetap menjadi tempat pulang yang nyaman. Penduduk yang ramah, sungai tempat mandi-mandi, gelanggang bermain masa kecil, selalu terkenang meski sejauh dan selama apa pun di perantauan.
Selain memperbaiki kondisi ekonomi, merantau juga bertujuan mencari ilmu pengetahuan. Terbatasnya akses pendidikan di kampung—khususnya tingkat sarjana—memaksa remaja-remaja kampung pergi ke kota demi memperoleh pendidikan yang lebih memadai. Namun, kerap timbul masalah lain. Remaja kampung yang berkuliah di kota berhadapan dengan situasi sulit; menuntut ilmu sambil memikirkan masalah perut.
Cerpen “Debat Kusir, Jalan Takdir” dan “Rian, Rokok, dan Kopi” mewakilkan masalah ini. Mahasiswa yang mestinya fokus menyerap ilmu, dipusingkan oleh dompet kosong sementara perut keroncongan. Ibu kos terus menceracau minta sewa kontrakan sedang ibu di kampung belum mentransfer uang bulanan. Situasi tersebut menuntut mahasiswa bekerja serabutan untuk menambah uang jajan. Urusan perut mendahului urusan perkuliahan. Urusan perut tak selesai-selesai, kuliah terbengkalai.
Situasi ini bertalian dengan cerpen “Toga untuk Ayah, Doa untuk Amak”. Ketika seorang anak lalai menyelesaikan kuliah, ada orang tua yang selalu menunggu kabar wisuda. Namun, harapan orang tua justru menjadi tekanan dalam menyelesaikan kuliah. Hal ini diperumit lagi dengan teman-teman sekampung yang sudah tamat, adik-adik yang akan bersekolah, dan administrasi kampus yang pelik. Maka, ketika kabar wisuda sampai ke rumah, yang selesai bukan hanya kuliah, tetapi tanggung jawab pada orang tua.
Meskipun cerpen-cerpen dalam buku ini menampilkan tema yang akrab dengan keseharian, kebanyakan cerpen sayangnya hanya berupa informasi. Misalnya dalam cerpen “Gunung Padang Menyimpan Sunyi”. Tokoh Aku awalnya menceritakan kenangan di Jembatan Siti Nurbaya bersama Saipul, teman semasa kuliah. Kemudian menggambarkan tokoh Bu Engge, pedagang di Jembatan Siti Nurbaya yang otaknya ngeres karena lama menjanda. Cerita beralih dari sejarah Siti Nurbaya hingga gemerlap Festival Siti Nurbaya yang mendegradasi pedagang-pedagang kecil.
Cerpen “Jangan Panggil Aku Orang Padang” hampir sama dengan cerpen sebelumnya. Dimulai dari tokoh Aku yang bertemu Leman—teman lama dari Jakarta yang berlibur ke Padang, penyaramataan demografis Padang, penelusuran Gunung Padang, hingga sejarah dan mitos Siti Nurbaya.
Kedua cerpen ini lebih terlihat sebagai catatan perjalanan ketimbang sebuah cerpen. Semua hal yang berkaitan dengan Siti Nurbaya dan Gunung Padang seakan penting untuk diceritakan. Alur cerita jadi membosankan, hanya penelusuran tempat wisata yang tak jelas ujung-pangkalnya.
Plot yang penuh kejutan dan karakter tokoh yang konsisten, juga minim terlacak dalam kumpulan cerpen ini. Dalam cerpen “Buah Tangan Ayah”, plot yang mestinya penuh tegangan, malah diselesaikan dengan mudah. Ayah, sebagai tokoh yang gengsi dan penuh harga diri, dengan mudahnya menerima bantuan dari Siman, lawan politiknya. Ketokohan Ayah menjadi lemah sekaligus menegasikan sifat ayah yang enggan menerima bantuan. Anehnya lagi, Ayah masih menganggap pemberian tersebut adalah rezeki.
Suara narator dan penulis tak kentara bedanya. Narator dijadikan tunggangan oleh penulis untuk menyampaikan gagasan dan pendapat pribadi. Alur cerita bergerak tidak bebas dan kebanyakan cerpen larut dalam opini penulis. Penulis juga tidak menyediakan celah-celah yang membuat pembaca menduga. Terdapat upaya menyimpulkan dan memberi nasihat untuk mengakhiri cerita. Sehingga, cerpen-cerpen dalam buku ini tidak menarik dibaca berulang kali.
Kalaupun ada plot yang coba disembunyikan, narator memberikan kisi-kisi yang gamblang. Dalam cerpen “Pasar Janda” misalnya, tokoh Leman melihat dua sosok aneh di belakang warungnya yang diduga berbuat mesum. Leman mencurigai dua tersebut adalah Bujang, salah satu pelanggannya, dan Tinah, istrinya. Namun, narator menyebutkan bahwa “Terlihat dua sosok: pria berkumis menghadap cahaya—mirip bujang—dan seorang wanita yang memunggunginya” (hlm.26). Hal ini mengganggu kebebasan interpretasi karena pembaca dapat menebak “apa yang disembunyikan penulis” sehingga tak perlu dilakukan pembacaan ulang.
Hal-hal yang disayangkan dalam cerpen-cerpen di buku ini menjadi samar karena disajikan secara ringan. Permasalahan-permasalahan tidak disampaikan dengan amarah yang meledak-ledak, tetapi jenaka, menggelitik, dan penuh kritik. Tak perlu kening berkerut dan kepala yang berdenyut untuk membacanya. Cerita-ceritanya terasa bersahabat karena merangkum masalah-masalah yang akrab serta menghadirkan fenomena-fenomena yang luput padahal sangat dekat. Buku Apa yang Tak Kau Dengar dari Kota dapat menjadi bacaan saat lelah pulang kerja di kota yang sibuk dan membosankan, atau menjadi teman yang merawat kenangan tentang kampung halaman.
Dandri Hendika; lahir di Solok Selatan, 2003. Peserta Residensi Belajar Bersama Maestro Kementerian Kebudayaan 2025. Manuskrip puisinya “Belajar Menanggalkan Bulan” terpilih sebagai pemenang sayembara Payakumbuh Poetry Festival 2025.
- Mendoa Puriang: Kue Suci di Bulan Rajab ala Muslim Keturunan India di Padang - 23 Februari 2026
- Seni Tak Selalu Soal Kompetisi: Di Tengah Situasi Banjir 61 Siswa Kelana Gelar Karya - 15 Februari 2026
- Cerpen Kapiturunan – Risnandar Tjia - 8 Februari 2026

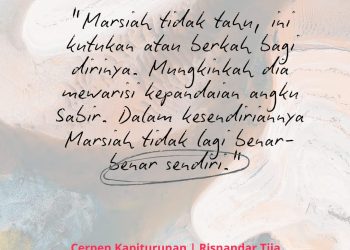

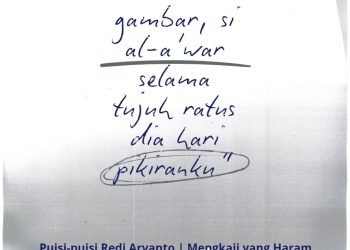



Discussion about this post