
Air sungai Batang Kapur berkilau keperakan disapu cahaya matahari siang. Di antara riak dan pusaran kecil, sampan-sampan kajang dengan muatan rotan, kelapa kering, dan keripik singkong melaju pelan. Sungai itulah jalan raya, satu-satunya penghubung Muaro Paiti ke dunia luar. Orang-orang di tepian sudah hapal, suara dayung yang mengiris air lebih nyaring daripada kokok ayam di subuh hari.
Tapi siang itu, kampung digegerkan kabar aneh: seorang pria tua ditemukan terbujur di buritan perahu miliknya. Ia dikenal sebagai penjual keripik, wajahnya ramah, tak punya musuh yang jelas. Beberapa pedagang yang lebih dulu menyusuri sungai berhenti, memandang tubuh renta itu yang kaku, seolah tengah tertawa namun mata sudah beku. Yang paling ganjil, ibu jari kanannya lenyap seolah dipotong dengan pisau tajam. Ada bekas darah kering, tapi selain itu tak ada luka terbuka berarti. Tubuhnya penuh lebam, seakan habis dihantam benda tumpul. Anehnya, muatan perahu tetap utuh; karung dagangan, uncang berisi uang, bahkan perhiasan murah miliknya pun tak tersentuh.
“Perampokan macam apa ini?,” bisik seorang pedagang, separuh takut separuh penasaran.
Berita itu menyebar lebih cepat dari arus sungai. Orang kampung bilang ini perampokan paling brutal sepanjang jalur Batang Kapur. Tapi sebagian lain menyangkal, jika benar perampokan, mengapa barang bawaanya utuh?
Menjelang sore, anak-anak yang mandi di tepi sungai menjerit menemukan sesuatu di balik batu besar: seorang gadis kecil tak lebih dari sembilan tahun. Wajahnya pucat, rambut kusut, tubuh gemetar. Ia menggigit pangkal ibu jarinya sambil menangis terisak, seolah rasa sakit di jari itu bisa menahan ingatan buruk yang barusan ia lihat.
“Jangan takut, nak…,” ujar seorang lelaki yang menemukan, sambil mengulurkan tangan. “Kami bukan penyamun. Kami akan mengantarmu pulang.”
Gadis itu ragu, lalu akhirnya digendong ke dalam sampan. Ia tak sanggup berkata-kata.
Polisi baru datang malam harinya, namun penyelidikan mereka tipis, sekadar formalitas. Mereka mencatat pria tua itu mati misterius, tanpa memastikan apa sebenarnya yang hilang. Tak ada satu pun dari aparat yang menanyai si gadis kecil, padahal hanya dialah saksi kunci. Orang-orang kampung hanya bisa bertanya-tanya: mengapa ibu jari pria tua itu yang diincar? Apa ada sesuatu di jari itu?
Beberapa orang tua di lepau kopi berbisik-bisik mungkin ada cincin pusaka di sana, cincin cap mohor ulayat adat, simbol sah kepemilikan tanah dan sungai. Cincin itu diyakini diwariskan turun-temurun, hanya dikenakan oleh pemimpin suku tertentu. Tapi tak ada yang berani mengucapkannya lantang, takut terjerat fitnah.
Malam itu, sungai Batang Kapur berubah muram. Riak airnya seakan membawa bisikan: ada darah keluarga yang hanyut bersama arus. Gadis kecil itu dibawa pulang oleh kerabat jauh, namun bayangan tentang tubuh ayahnya di buritan sampan, dengan jari terpotong, menempel seperti cap yang tak bisa dihapus dari ingatan.
Sejak hari itu, kisah tersebut menjadi misteri turun-temurun di Muaro Paiti. Anak-anak tumbuh mendengarnya seperti dongeng kelam. Tak ada yang tahu siapa pelaku, tak ada yang tahu ke mana cincin pusaka itu pergi. Yang tersisa hanya sebuah cerita yang dituturkan berulang, seperti gema suara dayung yang hilang ditelan kabut.
***
Enam dekade berlalu sejak tubuh pria tua itu ditemukan di buritan sampan. Sungai Batang Kapur sudah tak seramai dulu; jalur darat memutus dominasi sungai, sampan kajang hanya tinggal cerita di mulut orang tua. Namun arusnya tetap deras, membawa jejak masa lalu yang enggan hilang.
Di sebuah rumah semi permanen di pinggir Muaro Paiti, Leman baru beberapa bulan menjabat sebagai kepala pabrik pengolahan gambir. Ia kembali dari Padang, menerima tawaran kerja yang awalnya ditolak oleh ibunya. Baginya, ini kesempatan pulang kampung, meski asing, meski kenangan masa kecil hampir nihil. Pabrik tempat ia bekerja berdiri di tepi jalan aspal kasar, di kelilingi ladang gambir dan sedikit hutan ulayat. Setiap pagi, pekerja berdatangan membawa hasil panen, menimbang, lalu menjual pada pabrik. Di balik hiruk-pikuk itu, Leman sering melarikan diri ke lepau kopi Mak Uncu, satu-satunya lepau di depan gerbang pabrik.
“Bukankah ini kampung bapak juga, Leman?,” tanya Mak Uncu sambil menyuguhkan kopi. “Meski kau tak lahir di sini, darahmu ada di tanah ini.”
Leman hanya tersenyum tipis. Ia tak banyak bicara, lebih sering mendengar. Tapi ada sesuatu yang tak selesai di wajahnya—seperti ada pertanyaan yang terus menekan dari dalam.
Sore itu, saat kembali ke rumah tua peninggalan kakeknya, Leman memberanikan diri membuka rak kayu di kamar ibunya. Rak itu sudah lama terkunci, tapi kuncinya mudah ditemukan di bawah anyaman tikar pandan. Bau kertas tua menyeruak ketika pintu rak dibuka. Di dalamnya, bukan perhiasan, bukan barang pusaka, melainkan tumpukan buku catatan harian dan potongan puisi yang tak pernah dipublikasikan. Tulisan tangan halus, jelas milik ibunya. Leman membaca salah satunya:
“Sungai menyimpan suara, lebih banyak daripada manusia berani mendengar.
Jari yang hilang bukan karena pisau semata,
tapi karena ia memegang kunci yang tak boleh diwariskan sembarangan…”
Leman tertegun. Kata-kata itu terasa bukan sekadar puisi, melainkan pesan tersembunyi. Ia membaca lagi catatan lain; ada nama-nama orang yang tak ia kenal, ada tanggal-tanggal dari tahun 1960-an, ada sketsa sederhana tentang cincin berbentuk bulat dengan ukiran pucuak rabuang—lambang khas Minangkabau.Jantungnya berdegup. Ibunya tahu sesuatu tentang kematian pria tua di perahu itu.
Malamnya, ketika lampu minyak menyala redup di rumah, Leman duduk lama menatap buku catatan ibunya. Perlahan kepingan ingatan kecil yang kabur muncul: suara ibunya waktu ia masih kecil, pernah berpesan agar jangan pernah percaya penuh pada cerita orang kampung tentang sungai. Bahwa sungai bisa menelan rahasia keluarga. Ke esokan harinya, ketika ia singgah lagi ke lepau, Mak Uncu menatapnya lama, seperti tahu Leman sedang membawa sesuatu dalam pikirannya.
“Kau sudah buka rak itu, kan?,” tanya Mak Uncu pelan, sambil menuang kopi.
Leman hampir menjatuhkan cangkirnya. “Mak tahu?”
“Sudah saatnya kau tahu juga,” jawab Mak Uncu, menunduk. “Jangan kira cerita tentang perahu tua itu hanya dongeng. Ada darahmu di sana, Leman. Ada luka yang ibumu sembunyikan sampai ia menutup mata.”
Leman terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang baru saja mengiris selaput kabut di kepalanya. Ternyata ia terhubung langsung dengan misteri yang selalu dianggapnya mitos.Dan di saat bersamaan, Leman sadar. Ia tidak bisa lagi lari.
Hari-hari Leman di Muaro Paiti terasa makin aneh sejak ia menemukan catatan ibunya. Setiap ia baca, bait-bait itu seperti berbicara langsung padanya. Ada satu catatan yang paling mengganggu:
“Uda hilang di buritan. Jari yang diputus bukan untuk merampas harta, tapi untuk merampas marwah. Cincin itu, tanda pusaka kaum, tak lagi kembali.
Dan anaknya, yang belum tahu apa-apa, kutitipkan pada nasib.”
Nama “Uda” membuat tubuh Leman merinding. Uda—begitulah orang Minang menyebut kakak laki-laki. Itu berarti pria tua yang mati di buritan pada tahun 1960-an adalah pamannya sendiri. Leman menutup buku dengan tangan bergetar. Ia merasa seolah sedang ditarik mundur ke perahu tua di Sungai Batang Kapur. Ia membayangkan sosok pria renta yang terkekeh sebelum nyawanya direnggut, jempolnya dipotong, cincin pusaka raib.
“Kenapa rahasia sebesar ini disimpan, Mak?” gumam Leman.
Kabar anehnya, sejak Leman masuk pabrik, Lambe merupakan seorang toke paling besar di Muaro Paiti—terlihat sering menempel padanya. Lambe suka datang ke lepau, pura-pura basa-basi, menanyakan kebijakan ekspor. Tapi tatapan matanya menusuk, seperti ingin memastikan Leman tak keluar jalur.
Suatu sore, ketika hujan turun deras dan listrik pabrik padam, Lambe datang ke rumah Leman. Ia duduk di kursi rotan, basah kuyup, tapi wajahnya tegang.
“Leman. Kau tahu, kan, kenapa ibumu tak pernah mau pulang kampung? Kenapa dia tinggalkan tanah ini?”
Leman menegakkan tubuh. “Kenapa, Pak Lambe?”
Lambe tersenyum miring, “karena dia tahu darahnya pernah berlumuran di sungai. Karena cincin yang hilang di jari uda-nya, sampai sekarang masih berputar di tangan orang yang salah. Kau pikir pabrik ini hanya tentang gambir? Tidak, Leman. Ini tentang warisan yang jauh lebih tua dari daun-daun itu.”
Leman teringat catatan ibunya. Tentang cincin pusaka. Tentang “marwah” yang dirampas. Ia menahan napas.
“Pak Lambe,” suaranya bergetar, “apakah… cincin itu ada pada Anda?”
Lambe tidak menjawab. Ia hanya tertawa, tapi tawanya kering, getir.
“Ada yang lebih tua dari aku, Nak. Kau masih belum mengerti. Sungai tidak pernah menghapus darah. Ia hanya menyimpannya di dasar.”
Malam itu, Leman tak bisa tidur. Ia berjalan ke rak lagi, mencari catatan lain. Kali ini ia menemukan selembar kertas yang berbeda dari puisi lain: bukan bait, tapi semacam pengakuan. Tulisannya hampir pudar, tapi masih bisa dibaca.
“Jika kelak anakku pulang, jangan biarkan ia dibutakan oleh manisnya dunia. Uda-mu mati bukan karena dagang, tapi karena perselisihan adat. Cincin itu bukan perhiasan, melainkan tanda kaum. Barangsiapa memegangnya, dialah yang dianggap pewaris tanah ulayat. Dan aku takut, dendam itu belum mati…”
Leman tertegun. Semua mulai jelas. Kematian pria tua di buritan bukan sekadar pembunuhan, melainkan perebutan hak ulayat. Cincin pusaka yang terpotong bersama ibu jari adalah kunci legitimasi adat. Kini ia mengerti kenapa ibunya menolak pulang: ia takut anaknya terseret dalam dendam yang belum padam.
***
Di lepau besoknya, Leman menatap Mak Uncu lama-lama. “Mak… siapa sebenarnya yang pegang cincin itu sekarang?”
Mak Uncu menaruh kopi di meja, lalu menatap lurus ke mata Leman. “Pertanyaan itu jangan kau ajukan sembarangan, Nak. Banyak orang masih hidup dari darah lama. Kalau kau salah sebut, bisa terbakar kampung ini.”
“Jadi Mak tahu?,” desak Leman.
Mak Uncu menarik napas panjang, “yang jelas… Lambe bukan hanya toke gambir. Ia adalah anak dari orang yang menyingkirkan pamanmu di perahu dulu.”
Leman membeku. Kata-kata Mak Uncu seperti hantaman palu. Jadi selama ini, orang yang duduk minum kopi bersamanya, yang pura-pura ramah, adalah keturunan langsung dari pihak yang membunuh pamannya.
Hari itu langit Muaro Paiti mendung. Sungai Batang Kapur bergemuruh lebih deras dari biasanya, seakan menyimpan rahasia yang hendak memuntahkannya. Leman berdiri di tepi sungai, memandang arus coklat yang berlari tanpa henti. Ia menggenggam catatan ibunya yang lusuh. Kata-kata itu terus terngiang; “Barangsiapa memegangnya, dialah yang dianggap pewaris tanah ulayat.”Dan kini ia tahu, cincin itu masih ada.
Di lepau, bisik-bisik mulai beredar. Orang-orang tua berbicara lirih;
“Lambe makin kuat, semua tanah gambir masuk genggamannya.”
“Apa karena cincin itu? Entahlah, tapi aku lihat ada cincin besar di jarinya, mirip pusaka kaum.” Kata-kata itu menusuk hati Leman.
Sore itu, Leman memberanikan diri mendatangi rumah besar Lambe. Rumah papan kayu tua itu berdiri di dekat pohon beringin, menjulang seperti saksi bisu dari masa lalu. Lambe sudah menunggu. Ia duduk di kursi goyang, asap rokok kretek mengepul di sekelilingnya. Jarinya berkilau. Ya, di sana ada cincin besar, berukir motif khas Minang, hitam keemasan.
“Ini yang kau cari, Leman?,” tanya Lambe, sambil mengangkat tangannya.
Leman tercekat. “Itu… pusaka kaum ibuku.”
Lambe tersenyum tipis. “Ibuku yang merebutnya. pamanmu sudah kalah sejak malam itu di perahu. Sungai yang menelannya. Kau mau melanjutkan dendamnya, hah?”
Leman maju selangkah, suaranya bergetar tapi tegas.
“Pamanku mati bukan karena kalah. Ia dibunuh. Cincin itu diseret dari jarinya dengan darah. Kau tahu, Lambe, benda itu bukan sekadar emas. Itu marwah keluarga. Kau tidak berhak mengenakannya.”
Lambe tertawa keras, pahit, hingga kursi goyang berderit.
“Marwah? Marwah hanya milik orang yang sanggup mempertahankannya! Kau pikir adat peduli siapa yang benar? Tidak, Leman. Adat hanya tunduk pada siapa yang berkuasa.”
Ketegangan meledak. Leman nyaris meraih tangan Lambe, tapi lelaki tua itu berdiri cepat, menahan pergelangan Leman dengan cengkeraman kuat.
“Kau masih muda. Jangan bawa kampung ini terbakar hanya karena sejarah lama. Diamlah, seperti ibumu dulu. Itu lebih bijak,” desis Lambe.
Leman teringat wajah ibunya; muda, cantik, menulis bait-bait puitis penuh luka. Ia memilih diam, mengubur rahasia. Tapi hatinya hancur.
Tidak, pikir Leman. Ia tidak bisa diam.
Malam itu, Leman kembali ke tepi sungai. Bulan purnama pucat tergantung di langit. Mak Uncu menyusulnya, membawa pelita kecil.
“Nak,” katanya, “kau sudah lihat cincinnya?”
Leman mengangguk, wajahnya muram. “Itu benar-benar cincin pusaka. Bagaimana aku bisa membiarkan Lambe terus menipu semua orang?”
Mak Uncu menatap sungai, lama sekali, lalu berbisik:
“Kalau kau singkap rahasia ini, dendam lama akan bangkit. Bisa jadi kampung ini akan terbelah. Tapi kalau kau diam, kau ikut menanggung beban yang sama dengan ibumu.”
- Festival Akhir Tahun Steva 2025 : Membaca, Melihat, Merasakan, Mempelajari dan Merayakan - 10 Desember 2025
- Cerpen: Sales Event Organik (E.O) – Rori Aroka - 3 Oktober 2025
- Cerpen | Matinya Tukang Keripik – Rori Aroka - 29 Agustus 2025


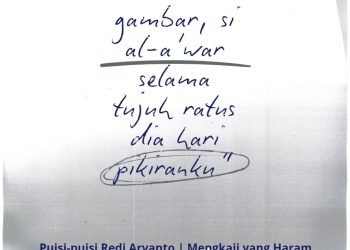




Discussion about this post