
Penulis, Jaka HB, Editor at Large Roehana Project Society of Indonesia Environmental Journalists Mongabay Indonesia
Beberapa hari ini saya kesal dengan nyamuk. Di mana-mana nyamuk. Kalau saya bicara ini ibu saya paling bilang; patahkan kaki nyamuk tu!. Tapi sudah jutaan kaki nyamuk yang saya patahkan, mereka masih belum gentar juga. Sementara itu angka demam berdarah meletup-letup tiap tahunnya. Pada bulan-bulan tertentu naik banyak, membuat takut. Pemerintah melulu mengatakan itu karena gaya hidup sehat masyarakat, padahal menurut orang-orang pinter di kampus-kampus itu penyebabnya kompleks. Salah satunya naiknya suhu, penahan uap panas kayak pohon-pohon udah ga ada, nyamuk-nyamuk di hutan, di semak-semak yang biasa mengisap darah babi, rusa, harimau atau lainnya, terusir dari rumah mereka, karena mereka butuh makan, pemukiman manusia tentu jadi lokasi menyenangkan. Suhu semakin naik, perkembangbiakan mereka semakin cepat.
Saya menulis itu waktu di Jambi. Tahun 2020 saya pindah ke Padang, berkeliing SUmatera Barat. Sebuah provinsi yang mendaku dirinya paling berguru pada alam. Alam takambang jadi guru. Tapi ternyata ada variasi lainnya untuk beberapa kelompok: Alam takambang untuk ditambang. Tapi alam takambang jadi guru ini sepertinya memang betul-betul nyata di sini. Tidak hanya ada di tempelan seminar, baliho pemerintah atau sambutan. Alam bener-bener jadi guru yang mengajari kita secara intensif, bentuknya? Ya itu. Melalui banjir bandang, longsor, kebakaran hutan dan lahan, buat ngajarin kita efek dari hutan yang ditebang dan sungai yang ditambang serampangan.
Mungkin kalau alam benar-benar jadi guru, berarti kita murid yang tipikalnya suka bolos, nyontek dan menyalahkan guru kalau nilainya jelek. Kayak banjir disebabkan oleh hujan dan alam yang semakin tidak menentu. Tentu saja racauan saya ini bisa dihubungkan dengan bagaimana tambang-tambang emas ilegal, tambang pasir ilelag, penebangan liar di hutan, penanaman sawit dalam hutan, penggunaan energi kotor yang serampangan, penggunaan ruang laut yang tidak diperhatikan, mengapa perbukitan di solok mengalami kekeringan padahal lanskapnya tidak gersang, mengapa Solok mengalami angka stunting tinggi padaal mereka penghasil sayuran, mengapa konflik agraria di pasaman barat tak usai-usai dan ternyata ada andil ninik mamak dan banyak lagi.
Sementara itu alam selalu disalahkan dan dibilang penyebab bencana-bencana ekologis. Padahal dalam petata petitih minang yang saya dapat dari diskusi ka diskusi: Bumi laweh bapadang lapang. Gunung indak runtuh karano kabuik.. Laut ndak karuah krn ikan. Modernitas yang Cair Saya ingin berkaca dari bagaimana semua struktur lepas, berubah dan sulit ditebak seperti cuaca. Zygmunt Bauman– filsuf dan sosiolog dari Polandia– menyebutnya kondisi ini seperti judul bukunya Liquid of Modernity atau modernitas yang cair. Struktur terlepas dari fungsi moralnya. Dari struktur-struktur terkecil seperti keluarga, warga sekitar dari RT-RW Kecamatan, pemerintahan sirkel-sirkel berkuasa, struktur adat, korporasi dan banyak lagi. Posisi-posisi yang seharusnya melindungi–sesuai patriarki yang tertanam dalam nilai matrilinealnya orang minang– menjadi posisi-posisi yang mengancam. Ayah yang memperkosa anak-anaknya, ninik mamak yang menjual tanah kaumnya, kerusakan lubang tambang yang tidak direklamasi dan janji-janji hijau yang tak pernah bisa ditukar dikedai. Bahkan mereka malah seringkali hanya memberikan bom yang dibungkus dengan daun pisang. Bauman mengutip Deleuze dan Guattari bahwa kita tak lagi percaya pada totalitas purba yang pernah ada, atau pun pada ottalitas akhir yang menanti kita di suatu titik di masa depan. Dia kemudian mengatkan definisi manusia sebagai manusia yang ditentukan oleh posisinya dalam masyarakat sudah berakhir.
Pada gilirannya yang menentukan adalah perilaku dan tindakannya. Tidak lagi diarahkan oleh norma-norma sosial dan pembelaan oleh aktor sosial oleh kekhasan budaya dan psikologis mereka. Semua itu tidak lagi berasal dari institusi sosial atau pin prinsip universal. Lantas kita semua terjebak dalam–apa yang dikatakan Paulo Freire– kesadaran Naif. Kita nyaman dalam kondisi stabil, kita tahu banyak masalah dan cara menyelesaikannya tapi diam. Terkadang malah ada dalam tahap kesadaran magis yang merasakan ada yang aneh dari stabilitas ini tapi kemudian menganggap semuanya takdir. Ya, semuanya takdir. Kita merasa terlepas dari struktur-struktur yang sebenarnya lahir sebagai penyebab semua tanda-tanda kehancuran ini. Keterlepasan ini tak lahir dari oplet yang kosong tanpa penumpang dengan tujuan ke pasar raya. Tentu saja tujuan oplet itu mengantar penumpang ke pasar dan penumpangnya adalah dosa-dosa pencerahan barat dari dualisme cartesian. Descartes memisahkan tubuh dan jiwa dan menurut Farabi Fakih menjadi dasar dari semua kebijakan antroposentris yang menganggap manusia ada di atas alam dan berhak memanfaatkan alam sehabis-habisnya.
Berbeda dengan Leibniz yang bilang kalau tubuh dan pikiran itu satu. Atau kalau boleh saya adopsi secara serampangan, manusia menjadi satu dengan alam, manusia adalah salah satu bagian dari ekosistem di bumi, walau pun lebih sering jadi alien, tapi bukankah banyak ritual atau prinsip-prinsip yang membuat manusia dan alam itu saling menjaga. Mereka yang di pusaran kerusakan lingkungan Nasib–kata Chairil– adalah kesunyian masing-masing. Kesunyian ini saya rasa menempel pada orang-orang kelas ekonomi lemah saat kerusakan lingkungan mendera mereka. Korban kerusakan lingkungan adalah mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Nelayan kecil yang kena abrasi, petani kecil yang lahannya rusak, petani sawit yang tak punya jaminan kesehatan dan lahannya dirampas, tukang parkir atau pemulung yang anaknya terus menerus batuk karena polusi udara dan air di kota, yang tidak punya uang untuk bikin sumur sendiri agar dapat air bersih dan punya air purifier di ruang tamu mereka. Orang-rang yang tinggal di sebelah PLTU atau tambang semen dan batubara yang tak bisa memilih untuk pindah karena tanah semakin hari semakin mahal. Selain itu juga pekerjaan yang tak lagi bisa jadi pegangan. DNA kita yang mengatakan bahwa menjaga pohon, satwa dan tanah ada timbal balik mereka menjaga kita.
Kita lebih percaya dengan adat yang lebih menjadi panjangan untuk menutupi alam yang rusak. Seperti kata Bauman, dalam modernitas yang cair yang bisa kita lakukan adalah terus bergerak agar tidak tenggelam. Tapi bagaimana jika air laut terus naik, apakah kita tidak kelelahan berenang? Ya, selamatkan diri dong dengan mencegah kerusakan lingkungan, kenaikan suhu global dan cari dataran tinggi dan kurangi giat-giat merusak alam dengan efektif. Sumatera Barat masih memiliki orang-orang yang dengan sadar memilih bersuara. Mereka yang ada di Danau Singkarak dan mempertanyakan solar panel terapung, mereka yang terancam geotermal, mereka yang tergusur oleh jalan tol, mereka yang terancam tambang pasir, mereka yang mengalami kerugian karena kerusakan lingkungan. Mereka bicara bukan karena nilai-nilai konservasi yang lahir dari ruang dingin, tapi dari hidup yang semakin brengsek. Greenwashing Greenwashing membutakan kita pada solusi sebenarnya. Untuk menerangkan definisinya, saya cerita sedikit sejarahnya. Pada tahun 1986 hidup seorang pria bernama Jay Westerveld, orang Amerika dan juga aktivis lingkungan.
Dia menginap di hotel yang katanya ramah lingkungan. Dia menemukan tulisan tolong jangan ganti handuk setiap hari, kami ingin menyelamatkan lingkungan. Tapi Jay tahu itu hanya akal-akalan untuk menghemat biaya laundry, bukan niat tulus jaga lingkungan, Sebab pada saat yang sama hotel itu ekspansi kemana-mana dan merusak kawasan pesisir. Karena itu dia menyebutnya greenwashing, pura-pura peduli untuk kepentingan citra dan keuntungan. Greenwashing muncul di perusahaan minyak yang memasang ikan yang memajang gambar daun dan anak kecil, pabrik semen yang mengklaim menanam sepuluh ribu pohon–padahal mereka menghancurkan 1000 bukit batu kapur, bank bikin program go green sambil mendanai PLTU Batu bara dan sawit ekspansif, atau produk air minum kemasan yang menulis 100 persen recycle tapi tak mengurangi produksi plastiknya. Apa yang bisa kita lakukan? Membaca dengan lebih dalam, bersuara kritis dan tidak elitis, bangun obrolan kecil di sekitar kita, dukung dan bangun alternatif nyata, berani mengatkan tidak memerlukan produk itu. Mengapa ini penting? Karena kalau tidak hati-hati kita akan dipakai sebagai alat legitimasi proyek merusak, dibisukan oleh estetika hijau yang menipu dan diubah menjadi konsumen yang merasa peduli tapi tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi. Karena kerusakan lingkungan bukan hanya soal pohon dan satwa tapi juga soal keadilan, kuasan dan pilihan moral di tengah dunia yang cair. Penutup Saya ingin sedikit serius di bagian ini.
Mungkin sekarang kita harus jadi murid yang tidak cuma hapal petuah jika alam menjadi guru, tapi tahu kapan harus angkat tangan dan bilang: Guru ini soalnya sudah tak masuk akal, kita mesti ubah cara belajarnya.
- BUKA TAHUN 2026, BAND STEVUNK DARI PADANG RILIS DUA LAGU BERNUANSA PROTES! - 23 Januari 2026
- PELESIRAN – Sebuah Catatan: Setelah UWRF, Apalagi yang Kau Cari? | Hasbunallah Haris - 10 Januari 2026
- Resensi: Antara Kota dan Kampung, Pecundang di Negeri Orang, dan Narator yang Berpetuah | Dandri Hendika - 8 Januari 2026



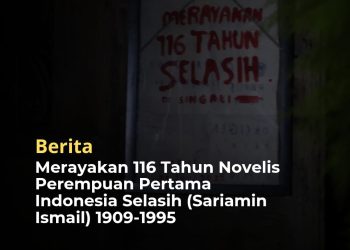



Discussion about this post