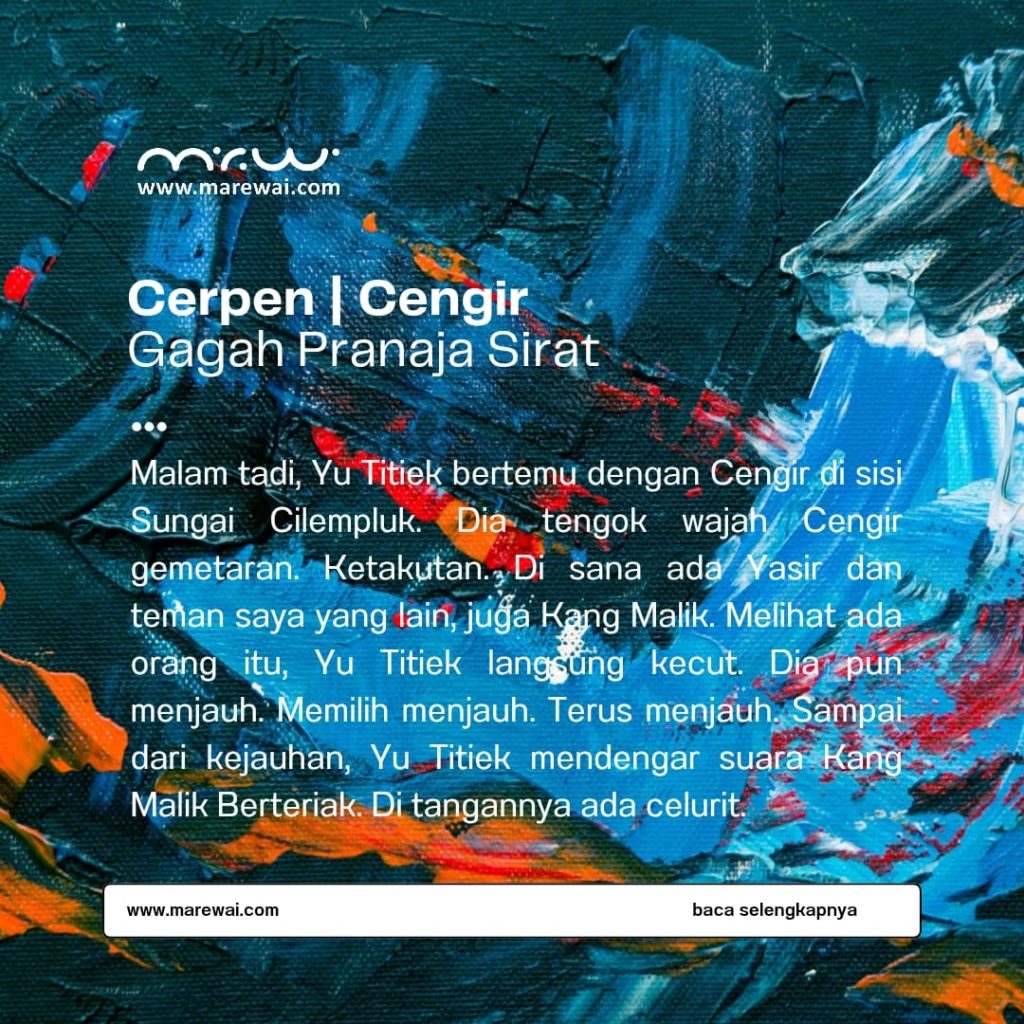
Cengir
KETIKA kami pastikan bahwa Cengir benar-benar telah meninggalkan kami: rumahnya kosong.
Sebatang rokok dan korek api masih terpancang di mejanya: tak berpindah tempat. Ranjang tidurnya masih baik-baik. Alas tikarnya tetap terbentang: kinclong dan mulus. Kelambu pemberian emaknya terpasang melingkar, seperti baru saja dia bereskan. Barang-barang simpanannya juga nihil digerogoti tikus atau rayap, masih tersusun rapi di atas dua buah lemari. Tapi lampunya sudah padam. Gelap. Seolah-olah penghuninya mendadak diculik hantu kebun pisang. Tidak ada tanda-tanda perpindahan. Tidak ada isyarat apapun dari si Cengir.
Sekitar dua atau tiga hari lalu, kampung kami kedatangan mobil-mobil besar. Tamu-tamu besar pula. Mereka memakai jas hitam. Gagah sekali. Rambutnya selicin getah karet. Hitam dan mengkilat. Salah satu di antara mereka ada yang meminta untuk dipanggilkan Pak RT. Gegas, temanku – Yasir, yang sedang mencari udang batu di kali, tergopoh-gopoh menuju warung Yu Titiek dan menemui kami yang sedang merehatkan diri. Setelah itu, Pak RT memanggil Cengir dan mengajaknya ke perbatasan kampung. Tidak menunggu lama, tanpa sosok Pak RT – Cengir lalu pulang dan kembali bergabung bersama kami. Seperti biasanya, raut muka Cengir bahagia. Kedua sungut bibirnya tersenyum selebar gapura.
“He, tampak senang sekali kau, Cengir! Ada apa? Apa yang orang-orang kota itu bawakan kepadamu?”
Cengir tidak langsung menjawab. Wajahnya masih nyengir. “Hi-hi. Mereka itu tinggi-tinggi sekali, ya?”
“Lha, itu sudah jelas. Kau tahu, orang-orang kota di sana harus naik ke gedung-gedung pencakar langit. Lantainya berpuluh-puluh tingkat. Kalau kau dongak ke atas, kau bisa menjumput separuh awan. Pantaslah itu. Tubuh mereka telah berbaur!”
“Iya, aku tahu. Hi-hi,” balas Cengir, cekikikan. “Tapi mereka itu lucu sekali, ya?”
“Lucu bagaimana? He, apa yang orang-orang kota itu bawakan kepadamu?”
Lagi-lagi Cengir tidak menjawab. Wajahnya masih nyengir. Namun, kami bisa lihat tangannya menyodorkan sesuatu. Sepucuk kertas bercoklat pekat. Di sana ada tulisan. Tulisan yang sama besar. Sontak, kami berpandangan ke arah Cengir. Mata kami melotot.
“Kau akan dipekerjakan di kota?”
Dengan sumringah, Cengir manggut-manggut. Kami kira mulanya Cengir bercanda. Maka hari itu, sambil lanjut menghabiskan kopi masing-masing, kami memilih tertawa-tawa. Ya, tertawa dengan perasaan sesuatu. Perasaan yang mengganjal. Perasaan yang tidak enak. Di samping itu, kami takut Cengir benar-benar akan ke kota. Dan ternyata prasangka kami itu tidak sepenuhnya salah. Rumahnya sekarang kosong. Dia telah meninggalkan kampung.
Nama aslinya Barman Sulapadri. Tinggal dekat dari Kali Cilempluk dan berbatasan dengan perkebunan bambu. Jika kalian hendak menyeberang dan melihat ada bayangan coklat samar-samar di balik rumpun bambu yang kian meninggi: itulah rumah si Cengir. Orang-orang menyebutnya ‘Cengir’ karena dia memang suka nyengir. Pekerjaannya hari-hari mengangkut batu kali, tapi lama-kelamaan berubah. Cengir jadi suka kerja serabutan. Dia banyak membantu warga. Membantu apapun itu, dia selalu terima. Sebab seringkali ketika diminta tolong: membenarkan irigasi, menggali sumur, mencari udang di lumbuk, menjaga kambing. Dia hanya bisa nyengir.
Entah cengirannya itu: senyuman yang tulus atau tertahan. Tapi yang pasti, dia menolong banyak hal. Terutama di kampung ini, jasa-jasa Cengir tiada tara. Meski tak jarang Cengir dibayar dengan tidak setimpal, dia hanya bisa nyengir. Upahnya biasanya berupa seikat bayam dan dua biji pala, dia terima sambil nyengir. Pekerjaannya tetap dilakukan dalam kondisi nyengir. Dan cengirannya itu, membuat semua mata yang melihat seperti bebas dari kekangan. Bebas dari segala beban.
Sampai Cengir telah benar-benar meninggalkan kami, rasanya itu seperti mimpi. Kampung saban hari jadi semakin sepi. Tidak ada lagi suara riuh orang-orang yang berebutan untuk meminta tolong padanya. Tidak akan ada lagi yang bisa membantu dan dibantu. Tidak akan ada lagi cengirannya: ini yang paling menyakitkan. Orang-orang mulai berwajah masam. Seakan-akan senyuman di kampung kami juga perlahan menghilang. Perlahan memudar.
Sesaat ditanya mengapa Cengir pergi oleh orang kampung. Kami menjawab, dia bekerja. Itu pertanyaan yang tidak pernah absen dari telinga kami sehari-hari. Maklum, orang-orang di sini sudah tua-tua. Sudah mulai pikun. Dan suatu waktu ketika kami ditanya apa pekerjaan Cengir. Kami hanya saling bersitatap. Garuk-garuk rambut.
“Oalah, Gusti… He! Dengar kalian sini. Orang-orang di kota itu biasanya dipaksa bekerja seperti beruk. Siang dan malam. Kadang diberi makan kadang tidak. Kalau mereka tidak bisa bekerja, layaknya seekor beruk. Mereka bakal dibuang ke laut. Dijadikan umpan paus!”
Maka ketika kami tanyakan demikian pula kepada Pak RT. Dia tidak tahu-menahu. Setiap kali ditanya orang-orang kampung, sama halnya seperti kami, Pak RT cuman mendesah malas dan mengangkat bahu. Acuh tak acuh sambil menghitung duitnya. Asap rokoknya mengepul-ngepul. Matanya bahkan tidak menatap kami.
“Lho, kalian tidak usah repot-repot kepusingan. Orang-orang kota itu baik. Percayalah. Kita tunggu nanti kabar dari Cengir. Pulang-pulang, bisa jadi tubuhnya sudah meninggi. Lebih tinggi dari pohon jati! Lagipula, badan lelaki itu gemuk. Bulat dan besar. Ya, kalian tahu? Seperti paha kerbau! Tak mungkin bakal dijadikan rumpon!”
Ah, dia selalu saja bersikukuh. Dan itu memang jadi lekat tabiatnya. Egois. Gila harta. Duit itu dia pegang-pegang seperti anak kucing, dimanja-manja, disayang-sayang. Dan sudah jadi tabiat Kang Malik – anak lakinya pula, menunggangi motor, disetirnya kencang-kencang, diputar-putarinya kampung. Pamer ceritanya. Tiap pagi kami dengar knalpot brong dari motor punyanya. Brrhhmm… Brrhhmm… Brrhhmm… !!
Begitu ibu-ibu kampung keluar disertai tangisan anak-anaknya yang gelumat. Kang Malik cuman pasang gaya, menggagah-gagahkan diri, lekas putar balik. Wajahnya ditutupi helm. Bunyinya pindah ke area lain.
Tiga bulan semenjak kepergian Cengir, muncul kasak-kusuk dan kekhawatiran orang kampung mengenai dia. Cengir tidak menelepon kami. Tidak memberi surat pula. Dia mana mengerti soal begitu. Lahir di kampung yang dikepung hutan-hutan lindung dan tumbuh bersama rumpun-rumpun bambu: membuat Cengir seperti liliput di antara besarnya teknologi perubahan zaman. Dia kerdil sekali. Saya takut dia tidak bisa bertahan hidup. Meski saya tahu, Cengir orang baik. Dia terlalu baik.
Kekhawatiran itu ternyata muncul pula dari Emak saya. Usia memasuki kategori sepuh dan mulutnya masih melafalkan kata-kata dengan betul: itu jelas sebuah keajaiban. Setelah dia sembuh dari penyakit ayan-nya. Emak baru bicara pagi ini. Tentu tentang Cengir. Ketika kami sedang menyeberang jembatan Sungai Cilempluk untuk memetik tunas bambu dan niat hati kepingin menjadikannya rebung. Emak memandang-mandang bayangan gubuk milik Cengir yang dari dulu tidak pernah direnovasi.
“Temanmu ada di warung si Titiek.”
“Hah?”
“Baru tadi. Pagi ini.”
“Yang betul, Mak?”
“Betul itu. Sini keranjangnya, biar Emak yang pegang. Baik kau susul temanmu itu di warung. Cepat, Nak. Ini sebab kau teramat sibuk membajak sawah, tidak tahu dunia luar. Cepat, Nak! Emak tadi lihat temanmu yang suka nyengir itu hadap-hadapan dengan Kang Malik. Wajahnya sungguh kecut!”
Lantas saya lari menemui Cengir yang diberitakan berada di warung Yu Titiek. Di sana, ternyata sudah ada teman-teman saya. Duduk bersebelah-sebelahan di atas dipan. Cengir yang kepergiannya seperti raib begitu saja dari rumahnya, tak dapat dipungkiri kalau sewaktu-waktu dia bisa datang begitu saja pula. Saya lihat wajah Kang Malik merah padam. Di hadapannya, Cengir tetap tersenyum. Tidak seperti yang dikatakan Emak.
Pertemuan itu ternyata hampir usai. Saya datang terlambat.
“Cengir akan kembali ke kota,” begitu kata Yasir.
“He, kenapa?”
“Kang Malik yang menyuruhnya.”
Menurut penuturan Yasir, Pak RT tengah sakit keras. Dulu, dia yang mendaftarkan Cengir untuk kerja di kota. Dan karena Cengir terlalu baik. Penghasilannya dikasih buat Pak RT. Konon, motor yang ditunggangi Kang Malik itu hasil kerja Cengir. Begitu pula benda-benda lainnya. Dan sekarang Cengir memilih balik, pulang. Katanya, dia sudah tidak sanggup. Namun, kembali dipaksa-paksa. Kalau tidak begitu, Pak RT bisa-bisa meninggal. Duitnya tidak ada. Sumbernya tidak ada.
“Cengir akan kembali ke kota,” begitu kata Yasir. “Dia tidak mau menemui kita.”
Persetan dengan peringatannya. Saya pun temui Emak yang sedang memasak rebung dan membawa satu bilah rantang. Saya langsung ke gubuk Cengir. Di kepala saya, hanya ada bayangan Pak RT yang kikir dan anaknya yang sok berkuasa, lalu saya remukkan kepalanya, saya lumat-lumat, dan saya buat sebagai pakan babi. Bajingan mereka. Sungguh bajingan!
Pintu gubuk Cengir tertutup. Lampunya tetap padam. Saya coba ketuk-ketuk mengucap salam. Cengir lalu keluar. Wajahnya tidak lagi nyengir. Saya ralat, ternyata benar yang dikatakan Emak. Rautnya kecut dan masam. Agak mengerikan. Tanpa berkata apa-apa, dia kembali menutup pintu. Saya paham gelagat dan segera minta diri. Sebelum pulang, saya taruh rantang berisi rebung itu di depan pintu bersama sepucuk surat dan beberapa uang. Niatnya, besok saya akan mengantar Cengir menuju kota. Kota yang tidak diketahui Pak RT dan segala niat busuknya.
Tapi pagi saya temukan: rumahnya kosong. Keadaannya sungguh berantakan. Semua barangnya terserak-serak. Ini terkesan ganjal. Ganjal sekali. Rantang itupun sudah tidak lagi di tempat awalnya. Gegas, saya pergi menemui Yu Titiek. Teman-teman saya malah tidak ada di tempat itu. Lengang.
“Cengir ke mana?”
“Anu…”
“Barman ke mana!”
“Anu… Mas, Cengir dibui.”
“Hah? Dibui?”
“Eh, tidak-tidak… Anu, Cengir sudah ke kota.”
“Yang bener kamu, Yu!”
“Eh, tidak-tidak-tidak… Itu, anu… Cengir ada di Sungai Cilempluk.”
“Sungai?”
“Iya.”
“Sama siapa?”
“Sama…”
Malam tadi, Yu Titiek bertemu dengan Cengir di sisi Sungai Cilempluk. Dia tengok wajah Cengir gemetaran. Ketakutan. Di sana ada Yasir dan teman saya yang lain, juga Kang Malik. Melihat ada orang itu, Yu Titiek langsung kecut. Dia pun menjauh. Memilih menjauh. Terus menjauh. Sampai dari kejauhan, Yu Titiek mendengar suara Kang Malik Berteriak. Di tangannya ada celurit.
Saya lalu terbirit-birit menuju Sungai Cilempluk. Di aliran airnya yang tidak terlalu deras, saya lihat benda putih terapit dua batu besar. Sebuah rantang tengah mengapung bebas. Rebungnya tumpah-tumpah, bercampur dengan air.
Gagah Pranaja Sirat, lahir dan menetap di bogor 12 Desember 2007. Sekarang, tengah menempuh pendidikan SMA jenjang kedua di sekolah Boash Ashokal Hajar. Di 1 tahun awal menulisnya, dia sudah mendapat lebih dari 50 juara dan prestasi dalam lomba kepenulisan fiksi serta non-fiksi. Baru-baru ini dia telah memenangkan dua cabang lomba sekaligus dengan sama-sama juara pertama pada cabang lomba cerpen dan cabang lomba puisi dalam rangka Festival Kenduri Sastra Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, serta cerpennya ‘Mondar-Mandir’ memenangkan juara kedua pada Bulan Bahasa Universitas Gadjah Mada. Profil prestasi tentang dirinya sudah diterbitkan dalam Majalah Inspiratif oleh Duta Inovatif Indonesia dan Youth Idea Community. Lihat ia lebih lanjut melalui instagramnya: @gahpraja.
- BUKA TAHUN 2026, BAND STEVUNK DARI PADANG RILIS DUA LAGU BERNUANSA PROTES! - 23 Januari 2026
- PELESIRAN – Sebuah Catatan: Setelah UWRF, Apalagi yang Kau Cari? | Hasbunallah Haris - 10 Januari 2026
- Resensi: Antara Kota dan Kampung, Pecundang di Negeri Orang, dan Narator yang Berpetuah | Dandri Hendika - 8 Januari 2026


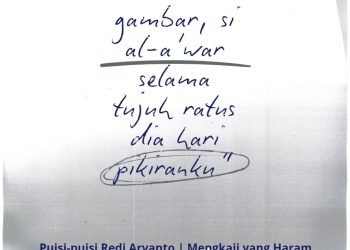




Discussion about this post